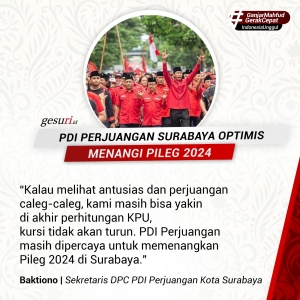Jika ada pertanyaan "siapa yang paling bertanggungjawab dari beredarnya isu-isu abadi seperti PKI yang tidak henti-hentinya dikipasi di media sosial?" jawabanya sudah pasti "politisi."
Mereka ini memiliki kepentingan politik untuk merebut kekuasaan dengan segala cara, tak terkecuali melalui pembentukan opini di dunia maya untuk meraih simpati publik secara masif.
Sungguh mengerikan bukan? Tapi inilah fenomena baru yang sekarang sedang terjadi. Banyak politisi yang menerapkan cara-cara kotor dengan memproduki berita-berita hoax, fake news atau false news hanya untuk mempengaruhi opini publik di dunia maya sehingga pada akhirnya publik mengiyakan ajakan atau opini yang disebarluaskan tersebut.
Mereka yang menjadi korban tentu saja publik dan obyek dari sasaran tembak para politisi kotor tersebut. Publik yang semakin malas untuk mencari verifikasi data dan fakta terhadap berita yang beredar di lini masa karena tersebut begitu mudahnya menerima sajian informasi yang belum tentu benar tersebut.
Isu-isu hoax, fake news dan false news terus diamplifikasi hingga membesar dan gaungnya semakin meluas. Ia bak bola salju yang terus menggelinding hingga akhirnya publik menelan mentah-mentah informasi yang berkeliaran di berbagai lini massa tersebut.
Jika ada kata yang menggambarkan lebih dari mengerikan, mungkin pantas kiranya untuk disematkan kepada politisi yang melakukan cara-cara kotor tersebut. Ya, inilah eranya post truth informasi. Sebagai dampak dari kehadiran media sosial yang semakin massif di era milenial ini membuat publik begitu mudahnya menerima informasi yang masuk ke akun lini masa mereka.
Post-truth sendiri merupakan istilah baru yang sempat meledak di tahun 2016 lalu. Post-truth makin tenar manakala kamus Oxford memasukannnya sebagai word of the year di sepanjang tahun 2016.
Karakteristik utama dari politik post-truth adalah:
a. Mengaduk-aduk masyarakat dengan hal-hal yang bersifat emosional.
b. mengabaikan data dan fakta.
c. Mengutamakan dan mem-viral-kan berita yang belum tentu kebenarannya atau palsu.
d. Mengkombinasikan gerakan populis dengan teori-teori konspirasi yang masih butuh diuji lagi kebenarannya
e. Mobilisasi narasi fiktif tentang figur atau peristiwa tertentu
f. Memoles ketidakjujuran dalam membangun opini untuk memperkuat posisi sosial figur, kelompok, atau kepentingan tertentu dalam masyarakat yang semakin terbiasa dalam peradaban televisual, online, android, dan media sosial.
Berkembangnya politik post-truth juga tidak bisa dilepaskan dari kegagalan institusi atau organisasi politik dalam meyakinkan publik tentang permasalahan-permasalahan tertentu yang tengah menjadi isu-isu besar dalam masyarakat.
Kondisi inilah yang menurut Paul Cho menjadikan politik desas-desus ala post-truth menjadi biasa lantas bagaimana awal mulanya, post-truth ini mengguncang dunia hingga gaungnya sampai ke Indonesia? Jadi begini, istilah post truth sendiri merujuk pada dua momen politik penting yang paling berpengaruh di tahun 2016 yaitu pertama kasus keluarnya Inggris Raya dari uni Eropa atau disebut dengan Brexit. Kedua, pada saat terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat.
Oxford lantas mendefinisikan post truth sebagai kondisi dimana fakta tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding dengan emosi dan keyakinan personal. Kondisi ini memang memuncak dalam dua politik yang cenderung lebih digerakan oleh sentimen emosi ketimmbang fakta. Sehingga dalam situasi itu, informasi-informasi hoax punya pengaruh yang jauh lebih besar dan lebih dipercaya oleh publik bila dibanding dengan fakta yang sebenarnya.
Donald Trump bisa menjadi Presiden Amerika dan mengalahkan Hillary Clinton yang cerdas itu dengan memakai strategi post-truth. Trump menyiapkan barisan politisi yang siap membentuk opini publik di lini massa. Mereka memproduksi berita bohong atua ujuarann kebencian untuk memenangi kompetiti politik di Amerika. Karenanya, kemenangan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada waktu itu bukanlah kemenangan yang bersih, melainkan hasil dari akumulasi ujaran kebencian yang terus diproduksi oleh barisan politisi bentukan Trump tersebut.
Warga Amerika Serikat sendiri saat ini lebih senang mendapatkan informasi dari media sosial ketimbang dari media konvensional. Selain itu, melalui pembentukan ujaran kebencian, emosi warga Paman Sam bisa dikendalikan dengan mudah.
Nah, pola-pola Trump tersebut menjadi presiden ini rupanya ingin dipakai oleh para politisi kita di Indonesia. Mereka pun menggunakan isu abadi yaitu SARA dan PKI kepada partai penguasa. Politisi kita sepertinya sudah kehabisan akal untuk melawan rezim yang berkuasa dengan cara-cara yang berkeadaban. Model-model menggunting dalam lipatan atau menikam dari belakang dipakai hanya untuk mencapai tujuan kemenangan yang semu.
Mereka pun memproduksi ujaran kebencian dan mengamplifikasinya menjadi suatu opini yang masif di dunia maya sehingga pemilik akun di dunia maya yang tidak tahu faktanya bisa termakan dengan mudah dan dikendalikan. Kita memang tidak bisa mengelak dari media sosial, dan kita harus akui bahwa sejak kehadiran media ini, peran media konvensional semakin hari semakin menurun dan beberapa ada yang mati.
Masyarakat juga sudah semakin malas untuk membaca media konvensional atau setidaknya melakukan verifikasi terhadap informasi yang sedang beredar. Sementara media sosial makin tidak tekontrol. Efeknya sudah pasti publik yang tidak memiliki sikap skeptis akan menerima semua informasi yang beredar tersebut.
Berbeda dengan media konvensional yang memiliki penyaringan berita atau gate keeper, kode etik dan regulasi serta tanggungjawab sosial yang di Indonesia dirumuskan sebagai bebas bertanggungjawab. Karena keterbatasan itulah media sosial dalam pembentukan opini publik, terus menggeser media massa konvensional. Media sosial tidak memiliki pembatasan, tanpa kontrol, bisa lebih cepat, mudah diakses dan bisa berinteraksi langsung dengan khalayak.
PDI Perjuangan Jadi Target Hoax
PDI Perjuangan sebagai partai penguasa tidak henti-hentinya diserang dengan isu PKI. Namun berdasarkan riset yang terbaru yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyebut bahwa opini kebangkitan PKI di masyarakat tidak terjadi secara alamiah melainkan sengaja dimobilisasi oleh kekuatan politik tertentu. Direktur SMRC Sirojudin Abbas bahkan dengan berani menyebut bahwa itu merupakan ulah dari para pendukung Prabowo termasuk mesin politik PKS dan Gerindra.
Sesuai dengan teori post truth, isu PKI hanya marak di media sosial. Isu ini sengaja dihembuskan untuk membangkitkan emosi kebencian. Namun sebenarnya di dunia nyata, isu PKI itu sama sekali tidak ada. Jauh lebih penting sekarang membahas masalah kemiskinan, ketimpangan sosial, pengangguran dan hal lainnya ketimbang mengurusi isu usang.
Hasl survei SMRC menunjukkan, orang-orang yang percaya isu kebangkitan PKI (12,6 persen dari responden) adalah mereka yang tergolong intensif mengakses berbagai media. "Terutama media internet dan koran," kata Direktur SMRC Sirojudin Abbas saat memaparkan hasil survey itu.
Bahkan hasil tabulasi silang dengan preferensi partai politik juga menunjukkan, mereka yang percaya PKI 'bangkit' kebanyakan merupakan pemilih PKS (37 persen), Gerindra (20 persen), dan PAN (18 persen). Uniknya lagi, mereka yang percaya PKI 'bangkit' justru berusia di bawah 21 tahun. Temuan ini mengonfirmasi bahwa isu kebangkitan PKI merupakan hasil mobilisasi opini kekuatan politik dengan menggunakan media sosial.
"Harusnya yang lebih tahu bahwa sekarang sedang terjadi kebangkitan PKI adalah kalangan warga yang senior. Sebab, mereka (para senior) lebih dekat masanya dengan masa PKI hadir di pentas politik nasional dibandingkan warga yang lebih junior, atau produk masa reformasi," kata dia.
Dari sebaran wilayahnya, mereka yang percaya PKI 'bangkit' mayoritas berada di wilayah DKI Jakarta, Banten, Sumatera Barat, dan Jawa Barat. Sirojuddin menuturkan, semua demografi tersebut beririsan dengan pendukung Prabowo.
Sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola, menyebut bahwa mereka yang percaya isu kebangkitan PKI, yaitu Muslim yang berasal dari Sumatera Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten konsisten dengan hasil survei SMRC sebelumnya tentang berdirinya negara khilafah. Survei SMRC tentang negara khilafah itu dirilis pada Juni 2017.
"Pada saat itu temuannya, mereka yang mendukung khilafah dan bersimpati kepada ISIS di daerah Sumatera Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, memang menunjukkan kelompok Muslim, kelas menengah, cukup santri, cukup fanatik. Jadi hasil survei ini konsisten," kata Tamrin.
Jadi kesimpulannya PKI itu memang sudah tidak lagi berkembang di Indonesia. Segala bentuk justifikasi naratif atas isu kebangkitan PKI yang diciptakan oleh politisi culas itu sama sekali tidak berdasar. Bahkan mereka dengan pintar mengemas bahwa ini sudah sangat genting sekali seolah-olah sudah terjadi bahaya laten. Tapi ada satu fakta yang tidak terbantahkan dan mampu menjawab bahwa PKI memang sudah mati termasuk dengan gerakan-gerakannya di Indonesia.
TAP MPRS No 25/1966 tentang pelarangan penyebaran ideologi komunisme di Indonesia yang sampai sekarang belum dicabut. Dan sesuai dengan TAP MPRS tersebut jika memang ada informasi tentang kebangkitan PKI aparat kepolisian dan militer bisa langsung menindak karena mereka memiliki kelengkapan struktur sampai tingkat kecamatan.
Sesungguhnya kemampuan mengaduk-aduk emosi dengan sentimen kebencian adalah bagian dari strategi post truth yang justru lebih membahayakan daripada sekedar isu PKI. Dan ini terus menerus dihembuskan hanya untuk memecah belah masyarakat. Karena itu sebaiknya bijaklah mewaspadai gerakan-gerakan post truth ini daripada sekedar termakan oleh isu bangkitnya PKI yang tidak bertanggungjawab.
Jadilah pengguna media sosial yang skeptis dan mampu berpikir konstruktif sehingga bisa memberikan pencerahan atas apa yang sedang terjadi saat ini. Sayangnya, pelaku media sosial yang konstruktif itu jumlahnya masih bisa dihitung dengan jari. (Berbagai Sumber)