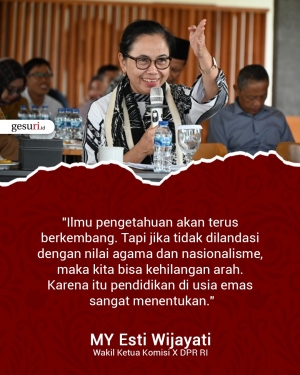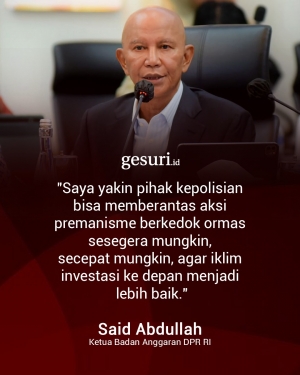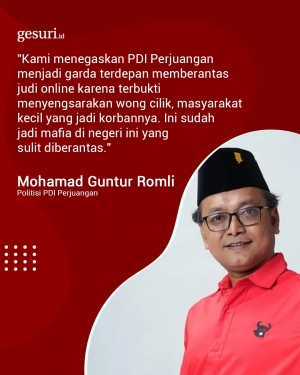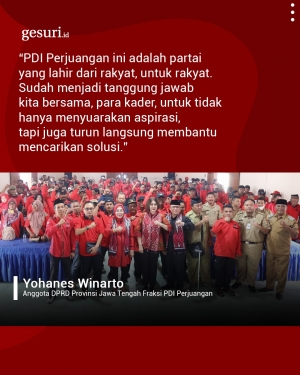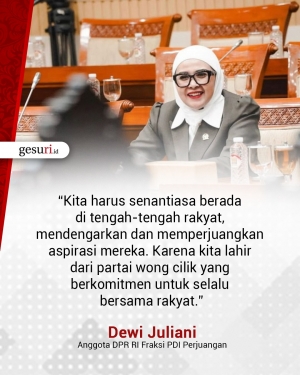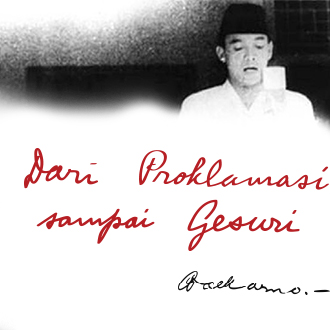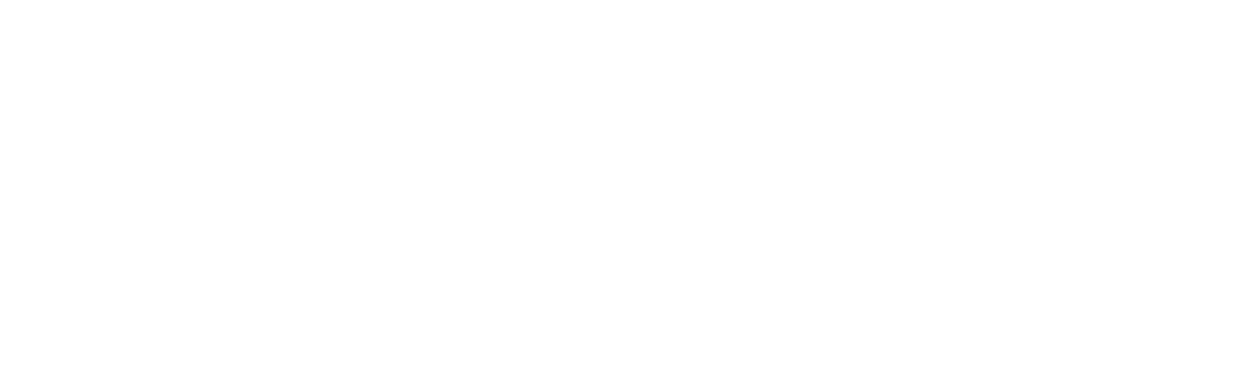Jakarta, Gesuri.id - Seratus hari bukan sekadar rentang waktu administratif; ia adalah cermin awal atas arah dan watak kepemimpinan. Dari kampus Universitas Jayabaya, kami menyaksikan geliat baru Jakarta yang lebih berdaya, lebih inklusif, dan lebih dekat pada warganya. Dalam era penuh dinamika dan tantangan pasca-pemindahan status ibu kota, Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno menunjukkan bahwa Jakarta bukanlah kota yang kehilangan makna strategisnya, melainkan sedang menemukan jati diri barunya sebagai poros pendidikan, budaya, dan keberadaban Indonesia modern.
Berdasarkan survei Litbang Kompas terbaru, mayoritas warga Jakarta menunjukkan apresiasi terhadap kinerja Gubernur Pramono Anung pada awal masa jabatannya. Sebanyak 64,5% responden menyatakan puas, sementara 30,1% belum puas, dan 5,4% masih menahan penilaian. Survei lain dari Ethical Politics bahkan mencatat tingkat kepuasan publik sebesar 77,73% terhadap kinerja 100 hari duet kepemimpinan Pramono–Rano. Ini bukan sekadar angka, melainkan pertanda bahwa kebijakan yang dijalankan mulai menjawab harapan kolektif warga kota.
Selain itu, yang terpenting citra pribadi Gubernur Pramono Anung mendapat penilaian positif dari 88,4% responden, mencerminkan hadirnya sosok pemimpin yang dipercaya lintas kelompok sosial. Wakil Gubernur Rano Karno pun tak kalah mendapat pengakuan, dengan tingkat kepuasan mencapai 57,5% dan citra positif sebesar 89,5%. Kepercayaan publik ini bukan hanya modal politik, tetapi juga modal sosial transformatif yang penting dalam membangun Jakarta sebagai kota cerdas yang tetap berpihak kepada rakyatnya—sebuah kota global yang berkeadilan.
Respons positif ini bukan hadir dalam ruang kosong. Tingkat kepuasan tinggi tercermin dalam berbagai program prioritas atau quick wins yang menyentuh akar kebutuhan masyarakat urban. Program pemutakhiran Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, misalnya, mencatat tingkat kepuasan sebesar 93%. Ini menegaskan bahwa pendidikan masih menjadi urat nadi harapan bagi keluarga Jakarta. Disusul oleh program pemutihan ijazah yang menyentuh 90% kepuasan responden, job fair (89%), transportasi umum gratis untuk 15 golongan (88%), serta pemasangan CCTV di kawasan permukiman (82%)—semuanya menunjukkan bahwa pemerintah daerah memahami denyut persoalan rakyat dan menjawabnya dengan kebijakan nyata, bukan retorika.
Dari sudut pandang pendidikan tinggi, capaian-capaian ini menunjukkan arah kebijakan yang berpihak pada rakyat—bukan hanya dengan niat baik, tetapi dengan keberanian politik dan eksekusi kebijakan yang terukur. Jakarta hari ini mulai menghidupkan kembali harapan sebagai kota belajar, kota layak tinggal, dan kota yang memberi ruang pada setiap anak bangsa untuk tumbuh dan bermakna.
Tinjauan Kritis-Positif terhadap Capaian Kunci
Pendidikan sebagai hak dasar warga kota telah diperluas melalui keberanian menuntaskan tunggakan ijazah dan memperluas jangkauan beasiswa. Ini bukan semata soal angka, melainkan cerminan keberpihakan kepada generasi Jakarta yang tersembunyi di pinggir jalan-jalan protokol kota—mereka yang kerap terhalang ijazah untuk sekadar melangkah ke masa depan. Pemutihan ijazah bagi lebih dari seribu siswa pada 100 hari pertama bukanlah solusi simbolik, melainkan langkah konkret yang menghapus sekat antara hak warga dan belenggu administratif. Sementara itu, perluasan KJP Plus dan KJMU menegaskan semangat konstitusi kita—mencerdaskan kehidupan bangsa—yang tak boleh hanya berhenti di meja visi pemerintah, tapi harus terasa hingga ruang keluarga kelas pekerja kota.
Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan sejatinya membentuk manusia yang merdeka secara batin dan sosial. Maka ketika negara hadir melalui bantuan pendidikan yang menyentuh mereka yang termarjinalkan, kita sedang menyaksikan aktualisasi nilai-nilai pendiri bangsa dalam bentuk kebijakan. Pemerintah Provinsi Jakarta di bawah kepemimpinan Pramono–Rano layak diapresiasi karena tidak sekadar mewarisi program, tetapi memperbaruinya dengan perspektif baru yang lebih sensitif terhadap realitas sosial kontemporer.
Selain pendidikan formal, langkah menghadirkan pelatihan kerja melalui Mobile Training Unit (MTU) dan job fair lintas wilayah adalah bentuk inovasi sosial yang patut dicatat. Dalam 100 hari, 960 warga telah dilatih, 32 di antaranya langsung terserap di dunia kerja, sementara lebih dari seratus mulai membuka usaha mandiri. Ini adalah narasi ekonomi kerakyatan dalam wujud nyata—bahwa pemberdayaan bukan hanya memberi bantuan, melainkan membekali keterampilan agar warga dapat berdiri tegak di tengah pusaran ekonomi kota yang kian kompetitif. Dalam bahasa Bung Karno, “revolusi harus berakar pada pemberdayaan rakyat,” dan pelatihan kerja ini adalah bentuk kecil namun signifikan dari revolusi keseharian itu.
Upaya memperluas ruang publik dan membuka taman kota 24 jam juga mencerminkan pandangan progresif terhadap kota sebagai ruang hidup, bukan sekadar tempat tinggal. Ruangruang ini bukan hanya estetika kota, melainkan panggung sosial di mana warga bisa merasa dimiliki dan memiliki. Demokratisasi ruang kota adalah bagian dari upaya melawan segregasi sosial yang selama ini membuat Jakarta terbagi antara yang memiliki dan yang terpinggirkan. Kota yang sehat secara sosial adalah kota yang membuka ruang bagi perjumpaan lintas kelas, usia, dan profesi—sebuah prinsip yang kini mulai diwujudkan dengan serius.
Tak kalah penting adalah keberanian menginisiasi Jakarta Collaborative Fund, sebuah instrumen pembiayaan kreatif dengan spirit gotong royong modern. Dengan menyisihkan dana Rp3 triliun dari SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) dan mengarahkannya ke sektor yang memperkuat pelayanan publik, program ini menunjukkan visi fiskal yang tak hanya bertumpu pada belanja, tetapi juga pada investasi jangka panjang terhadap kesejahteraan kota. Bagi kalangan akademik, ini adalah sinyal positif tentang hadirnya 3 model tata kelola daerah yang tidak reaktif, tetapi strategis. Di tengah tekanan global terhadap ruang fiskal pemerintah, pendekatan ini dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan kemandirian pembangunan.
Secara keseluruhan, kita melihat adanya pola kepemimpinan yang tidak hanya merespons masalah, tetapi juga mencoba membongkar akar-akar ketimpangan melalui intervensi yang tepat sasaran. Kebijakan-kebijakan ini telah menandai bahwa pembangunan Jakarta tidak sekadar membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur sosial yang menjadi fondasi kota modern yang berkeadilan. Dengan cara ini, Pramono–Rano menunjukkan bahwa kota global bukanlah tentang gedung tinggi dan investasi besar semata, melainkan tentang bagaimana setiap warga merasa hadir dan dihitung dalam nadi pembangunan kota.
Kritik Konstruktif dan Harapan Akademik
Namun demikian, tantangan tak boleh disembunyikan di balik data dan grafik capaian. Masih kita temukan layanan publik yang belum merata dari sisi mutu maupun pengawasan lapangan. Sejumlah keluhan warga terhadap pengemudi mikrotrans yang ugal-ugalan, kurangnya akurasi jadwal, hingga pengabaian titik halte menunjukkan bahwa transformasi transportasi publik bukan hanya persoalan rute dan armada, tetapi juga soal disiplin pelayanan dan pembudayaan etika publik. Demikian pula dengan infrastruktur pelatihan kerja yang di beberapa lokasi belum dilengkapi perangkat keamanan dasar seperti CCTV, sehingga menciptakan rasa tidak aman, terutama bagi peserta perempuan dan kelompok rentan lainnya. Kekurangan ini perlu segera ditanggapi sebagai bentuk keseriusan dalam membangun bukan hanya program, tetapi juga ekosistem sosial yang aman dan beradab.
Transparansi dan pengawasan penggunaan dana publik juga masih perlu diperkuat. Inovasi pembiayaan seperti Jakarta Collaborative Fund adalah langkah strategis, namun kredibilitasnya akan sangat ditentukan oleh mekanisme kontrol yang terbuka dan partisipatif. Dalam hal ini, saya percaya bahwa kampus bukan sekadar menara gading, melainkan harus hadir sebagai mitra etis dan epistemik dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Universitas Jayabaya, siap menjadi bagian dari arsitektur audit sosial yang melibatkan mahasiswa, komunitas, dan pakar lintas disiplin dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan publik secara berkelanjutan. Ini sejalan dengan semangat Tri Dharma Perguruan Tinggi—khususnya pengabdian masyarakat dan riset yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga kota.
Lebih jauh, dalam upaya menjadikan Jakarta sebagai kota cerdas (smart city) yang mendunia, kami mendorong pendekatan digital yang inklusif dan berkeadilan secara politik, hukum, dan sosial. Dalam kerangka politik hukum progresif, digitalisasi kota tidak boleh sekadar dimaknai sebagai alat efisiensi administratif atau alat kendali teknokratik. Ia harus menjadi wahana pembebasan, di mana teknologi hadir untuk memperluas hak warga, bukan menciptakan stratifikasi digital baru. Dalam pandangan ini, keadilan teknologi menjadi bagian dari keadilan struktural, yang hanya mungkin tercapai bila perencanaan dan pelaksanaan smart city memperhitungkan kompleksitas akses, literasi, dan keberagaman kondisi sosial warga Jakarta.
Penataan sistem informasi, sistem pelayanan publik digital, maupun infrastruktur data perkotaan haruslah dibangun di atas prinsip partisipasi bermakna, transparansi algoritmik, dan keberpihakan kepada kelompok yang paling rentan—kaum disabilitas, lansia, pekerja informal, dan komunitas marjinal. Dengan demikian, digitalisasi tidak menjadi eksklusi terselubung, 4 melainkan instrumen demokratisasi yang konkret. Di titik inilah kolaborasi antara pemerintah daerah dan komunitas akademik sangat mendesak: agar transformasi digital tidak dibajak oleh paradigma pasar dan kontrol, tetapi dirancang dengan basis etik, historis, dan keilmuan yang kuat.
Lebih penting lagi, upaya membangun Jakarta sebagai kota global seharusnya tidak mencabut kota ini dari akar historis dan jati dirinya. Kita harus kembali membaca Jakarta bukan sekadar sebagai megapolitan modern, tetapi sebagai kota bandar—Jayakarta—yang sejak abad ke-16 menjadi simpul pertemuan budaya, kekuasaan maritim, dan gerak lintas manusia. Dalam kajian antropologis dan historis, Jayakarta adalah kota pelabuhan yang membuka dirinya pada dunia, namun tetap berpijak pada kekuatan lokal: kampung-kampung yang hidup, jaringan ekonomi rakyat, dan nilai gotong royong sebagai ruh kota.
Dengan demikian, pembangunan Jakarta hari ini dan ke depan haruslah menyambung warisan geografis, filosofis, dan sosiologis itu. Kota ini tak akan menjadi “global” jika kehilangan akarnya. Dalam bahasa Bung Karno, kita membangun dengan “kaki menjejak bumi dan kepala menatap langit.” Maka transformasi Jakarta haruslah membumi dalam keadilan sosial dan menjulang dalam visi peradaban.
Universitas Jayabaya meyakini bahwa kota yang besar membutuhkan pikiran-pikiran besar. Kami siap menjadi mitra strategis dalam merumuskan, mengkritisi, dan mendampingi transformasi Jakarta melalui riset, kajian multidisipliner, pengembangan pusat studi perkotaan, hingga forum publik berbasis warga. Kami percaya, Jakarta dapat menjadi laboratorium sosialpolitik urban terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara, jika ruang-ruang kolaboratif antar aktor—pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku ekonomi—diciptakan dan dirawat dengan kesetaraan dan kepercayaan.
Dalam konteks ini, sinergi antara ilmu pengetahuan dan keberanian kepemimpinan adalah keniscayaan. Pemerintahan yang visioner tidak cukup hanya dengan niat baik dan kerja teknokratis, tetapi harus dibimbing oleh pengetahuan, refleksi historis, dan keberanian moral untuk berpihak pada yang lemah. Seperti dikatakan Bung Karno, “pikiran yang sehat harus menjadi nyala dalam pembangunan bangsa.” Dan Jakarta, dengan segala kerumitannya—dari kampung-kampung tua yang terdesak beton hingga mimpi generasi mudanya yang tumbuh dalam lanskap digital—adalah tempat terbaik untuk menyalakan nyala itu: nyala nalar, nurani, dan narasi kemajuan yang tidak meninggalkan siapa pun.
Sebagaimana dilantunkan oleh Benyamin S, maestro rakyat Betawi yang memahami denyut kota ini lebih dari banyak pejabatnya, “Kota gede tapi hati jangan kagetan, harus tetep ngelindungin yang kecil-kecil juga.” Kalimat itu bukan sekadar petuah, tetapi pesan moral tentang bagaimana membangun kota besar tanpa kehilangan wajah kemanusiaannya. Jakarta tidak boleh menjadi kota yang gagah dari kejauhan, namun asing dan mencekik dari dekat.
Di sinilah, peran perguruan tinggi seperti Universitas Jayabaya menjadi penting— sebagai mitra kritis, mitra etis, dan mitra strategis. Dalam terang pengetahuan, kami siap hadir bukan hanya untuk mengamati, tetapi untuk ikut membentuk masa depan Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan. Sebuah kota yang maju karena ilmu, hidup karena seni, dan adil karena cinta pada warganya sendiri.
Penutup: Visi Bersama untuk Jakarta sebagai Kota Global yang Berkeadilan
Kota global bukan berarti kota tanpa akar. Sebaliknya, kota yang benar-benar mendunia adalah kota yang mampu merawat akar sejarah, budaya, dan nilai-nilai lokalnya, seraya membuka diri pada dialog peradaban global. Jakarta memiliki peluang historis dan tanggung jawab moral untuk menunjukkan kepada dunia bahwa modernitas tidak harus menindas tradisi, bahwa pertumbuhan ekonomi tidak harus meninggalkan keadilan sosial, dan bahwa teknologi tidak harus menjauhkan rakyat dari hak-haknya. Visi kami terhadap Jakarta adalah sebagai kota belajar yang manusiawi, di mana pendidikan tidak hanya mencetak tenaga kerja, tetapi membentuk warga negara yang kritis, peduli, dan berdaya.
Dalam jalan panjang menuju Jakarta sebagai kota global yang berkeadilan, Universitas Jayabaya berkomitmen menjadi mitra strategis pemerintah daerah. Kami siap memperkuat ekosistem pengetahuan melalui riset kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan pengabdian masyarakat berbasis keilmuan. Kami percaya bahwa pengetahuan bukan hanya untuk menara gading, tetapi untuk membangun peradaban. Di tengah perubahan zaman, ketika Jakarta memasuki babak baru pasca-pemindahan ibu kota negara, inilah momen untuk memaknai ulang peran kota: bukan sebagai pusat kekuasaan administratif semata, melainkan sebagai pusat energi sosial, budaya, dan intelektual bangsa.
Kami melihat, dalam 100 hari pertama ini, fondasi telah diletakkan. Harapan telah disulut. Dan kepercayaan publik, sebagaimana tercermin dalam survei dan sentimen warga, mulai terbangun kembali. Tugas kita bersama adalah menjaga bara itu tetap menyala, membesarkannya dengan kerja nyata, dan menjadikannya terang yang membimbing Jakarta ke masa depan yang inklusif, adil, dan bermartabat.
Dan dalam jalan panjang itu, kami dari Universitas Jayabaya siap turut berjalan bersama—menerangi langkah dengan ilmu, menguatkan pijakan dengan nilai, dan menyemai masa depan dengan cinta kepada kota ini dan bangsanya.