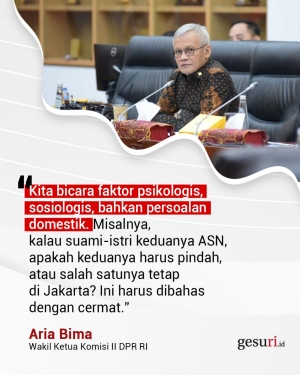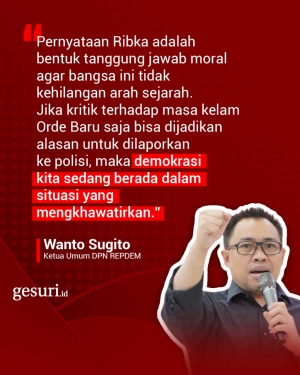SETIAP pemimpin tidak lahir begitu saja. Ia dilahirkan sebuah zaman. Seperti beras yang lahir dari benturan alu dan gesekan antarbulir padi. Ia punya daerah yang menjadi laboratorium dan tonggak penting awalnya menapaki politik nasional.
Dan, Surabaya, kota di mana Soekarno tumbuh sebagai remaja penuh vitalitas politik dan bergaul sangat intim dengan baron-baron pergerakan kebangsaan, menjadi napas pertama saat Megawati Soekarnoputri menjadi sampul depan sebagai politisi nasional. Itu terjadi pada pamungkas tahun 1993. Jawa Timur, bukan Sumatra Utara. Surabaya, bukan Medan.
Memang, naiknya Megawati Soekarnoputri ke pentas politik nasional di mana nama dan wajahnya menjadi headline media-media cetak merupakan ekses dari Medan. Kongres PDI ke-IV Medan yang berantakan pada pekan terakhir bulan Juli itu nyaris nama Megawati tidak ada dalam indeks keributan di gelanggang kongres. Selain deadlock, aksi tabrak jip dan baku pukul antarpendukung menjadi pemandangan selama lima hari di Wisma Haji Pangkalan Mansyur, Medan.
Aklamasi atas terpilihnya kembali Soerjadi mendapat penentangan dari PDIP (PDI Peralihan) dan Kelompok 17.
Nama-nama ini yang moncer dalam gebalau kongres ditutup tanpa pleno sebagaimana lazimnya, antara lain Sabam Sirait, Aberson Marle Sihaloho, Jacob Nuwawea, Alex Asmasoebrata, Achmad Soebagio, Budi Hardjono, Ismunandar, dan Soetardjo Soerjogoeritno.
DPP Karateker di Medan mengamanatkan Kongres Luar Biasa dengan pimpinan sementara dijabat Latief Pudjosakti dari PDI Jawa Timur. Dari Medan lalu bandul berpindah ke Surabaya di tahun yang sama di bulan terakhir. Sepanjang perjalanan dari Medan dengan tujuan ke Surabaya itu, nama Megawati Soekarnoputri masih belum terang-benderang muncul ke permukaan.
Sesuai namanya, kongres "luar biasa", Surabaya memang menjadi sesuatu yang "luar biasa". Sesuatu yang istimewa. Dua kota yang spesial bagi Megawati.
Yogyakarta, tentu saja, sangat istimewa bagi Megawati karena ia memang lahir di alam Republik yang dipayungi mega-mega dan pada akhirnya ia mendapatkan nama lengkap: Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri. Tahun ini, politisi liat yang lahir saat Republik dalam kondisi genting ini berusia 73 tahun.

Yang istimewa kedua adalah Kota Surabaya di mana ia naik ke panggung politik nasional untuk menakhodai PDI yang sepanjang tahun 1993 babak-belur oleh konflik internal yang mustahil untuk didamaikan. Surabaya adalah laboratorium pertama bagaimana berpolitik dalam badai dengan gulungan mega-mega hitam cakrawala perpolitikan nasional. Megawati yakin tuah Surabaya yang bukan hanya “kota sabung nyawa” di awal revolusi Indonesia, tetapi juga perkaderan politik diniyah bagi ayahandanya sebelum hijrah ke Bandung untuk mendirikan PNI.
Surabaya, dengan demikian, adalah lab politik awal dan mendasar bagaimana menata kontestasi politik dari konflik internal partai. Ributnya di Medan, damainya di Surabaya. Lebih kurang seperti itu.
Dalam perjalanan menuju Surabaya itulah nama Megawati mulai muncul dalam bisik-bisik di antara segala kepastian. Konferensi pendahuluan yang dilakukan cabang-cabang sesungguhnya mengerucut pada satu nama, Budi Hardjono. Saat konflik antarkader tak bisa ditenggang, muncul kerinduan dari PDI Solo kepada mereka yang dalam hemoglobin darahnya ada nama Soekarno. Di Jawa Tengah, saat nama ini dimunculkan Solo dengan segala keberaniannya, pengurus bergolak.
Bahkan, ada suara dari Kodam Jateng yang meremehkan bahwa yang diandalkan Megawati adalah nama besar ayahnya. Tak lebih dari itu. Atas pengerdilan dan nyinyiran seperti ini, Megawati menjawab tak kalah cueknya, "Terus, saya harus memakai nama Megawati binti Bejo atau siapa?"
Makin dekat dengan hari vonis pelaksanaan Kongres Luar Biasa (KLB), nama Megawati kian membumbung. Deklarasi yang menjadi tonggak keluarnya Megawati ke publik politik terjadi di Ibu Kota. Momentumnya di gelanggang literasi, saat Megawati menghadiri peluncuran buku tipis yang merangkum sepak-terjang politik dan apa yang ia pikirkan "membereskan" politik Indonesia.

Buku itu berjudul Bendera Sudah Saya Kibarkan. Tidak kebetulan belaka bila buku itu diluncurkan di Hotel Indonesia. Hotel pertama yang diresmikan ayahandanya jelang pagelaran Asian Games IV 1962. Buku dan momen peluncuran itu adalah tiket dan manifes Megawati untuk siap mengarungi politik nasional sebagai seorang pemimpin tertinggi partai.
Pada buku ini, Megawati menegaskan bahwa ia bukan ujug-ujug. Ia menerima pendidikan politik secara natural, secara diniyah, dalam keluarganya. Sukarno adalah politisi terbesar dalam sejarah Indonesia. Sukarno adalah ayah sekaligus gurunya. Tak ada sekolah formal politik yang diikuti Megawati karena pendidikannya ditempuh lewat homeschooling. Sekolah politik homeschooling itu diuji sepekan kemudian di Surabaya setelah peluncuran buku di Hotel Indonesia yang ramainya bukan main.
Tidak hanya itu, efek dari peluncuran buku itu dan kemudian disusul KLB, nama dan wajah Megawati merebut halaman depan koran dan majalah. Bahkan, majalah Tempo pada Desember 1993 berturut-turut tiga kali menjadikan wajah Megawati Soekarnoputri dalam satu bulan. Tidak ada politisi yang bisa “merebut” halaman depan seperti ini jika bukan tokoh yang mumpuni. Artinya, panggung politik Desember dalam perspektif yang dibungkus oleh media, Megawati menjadi sudah menjadi pemenang.
Jika media adalah media massa, artinya, Megawati tidak sekadar merebut kursi pemimpin partai secara formal, tetapi merebut hati publik, merebut per(hati)an masyarakat dalam budaya politik yang represif.
Pinjam judul coverstory majalah Tempo edisi 4 Desember 1993, “Maju terus, Megawati!”. Mari berangkat ke Surabaya; kota luar biasa untuk kongres yang luar biasa. (Bersambung)