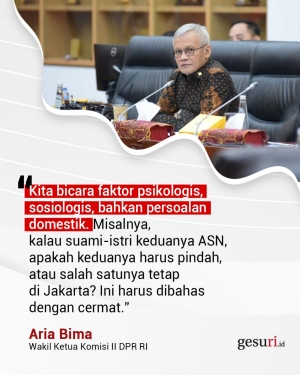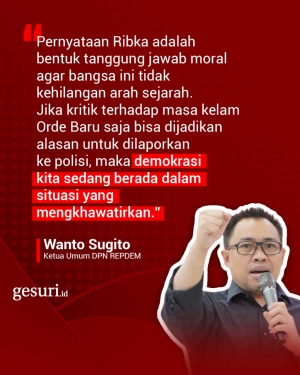Jakarta, Gesuri.id - "Jakarta, kota ku indah dan nyaman. Di situlah aku dilahirkan" penggalan lirik lagu berjudul Gang Kelinci yang dipopulerkan oleh Lilis Suryani ini rasanya seperti mimpi di siang bolong. Pasalnya, di hari jadi Ibukota Negara Indonesia yang ke 492 tahun ini, Jakarta masih saja nampak semrawut dan membuat warganya hilang kewarasan.
Meskipun sudah berusia nyaris lima abad dan 17 orang gubernur telah berganti serta pembangunan infrastrutur terus berlanjut dan berkembang seolah tiada pernah berakhir, Jakarta tetap 'begitu-begitu' saja. Tetap padat dan sumpek. Jangan ditanya lagi soal kemacetannya, mau-tidak-mau harus diterima. Kalau tidak, ya, "siapa suruh datang (ke) Jakarta."
Bagaimana tidak? Di atas lahan seluas 661.5 km2 semuanya dipepatkan. Mulai dari kegiatan bisnis hingga panggung utama politik, terpusatkan di Jakarta. Kota ini serupa magnet yang menarik banyak orang untuk berbondong-bondong datang dan mencoba peruntungan. Tak heran jika akhirnya kepadatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta saat ini mencapai 15.663 jiwa per km persegi dengan dengan jumlah penduduk mencapai 10,37 juta jiwa.
Lalu, apakah ini tandanya Jakarta memang ditakdirkan untuk menjadi kota yang tak layak huni hingga membuat warganya jadi hilang kewarasan? Pada dasarnya memeng Jakarta tak dirancang untuk menanggung jutaan penduduk, maksimal 800 ribu jiwa saja yang bisa ditampung. Namun, sejak lima dekade belakangan ini, jumlah penduduk justru kian membengkak berkali-kali lipat dan berdampak pada menjamurnya perkampungan-perkampungan kumuh.
Beruntung Jakarta pernah memiliki sosok gubernur yang revolusioner yaitu Ali Sadikin. Bang Ali -- sapaan akrabnya -- diangkat sebagai gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Soekarno pada April 1966. Sejak hari pertama menjabat, Bang Ali memang telah memiliki ide-ide untuk menjaga kewarasan hidup sebuah kota. Baginya sebuah kota bukan hanya membangun dan mengembangkan infrastruktur, tapi juga menjaga kewarasan penghuninya.
Daripada menggusur pemukiman penduduk, dia justru membuat program menata kampung demi membangun citra masyarakat yang guyub dan rajin bergotong royong. Namun, pada tahun 1960-an program terebut dinilai gagal. Pertumbuhan penduduk di ibukota justru tak terbendung dan kian meningkat dengan sangat cepat.
Untuk mengatasi hal tersebut, Bang Ali lantas menjadikan Jakarta sebagai pionir program Keluarga Berencana. “(Program) Keluarga Berencana jadi prioritas dan Jakarta menjadi pionir dalam hal tersebut,” ujar Bang Ali seperti dikutip dalam film dokumenter Wet Earth and Warm People karya Michael Rubbo.
Keresahannya soal laju pertumbuhan penduduk di Jakarta pun dia tuangkan melalui berbagai kebijakan, salah satuya operasi kependudukan dan menutup kota bagi pendatang baru atau yang dikenal dengan nama Operasi Yustisi. Namun, Bang Ali rupanya juga tetap menginginkan perlunya ruang hidup yang lebih luas demi ‘kesehatan’ warganya, maka dia pun mulai menggagas konsep kota Megapolitan yang kini dikenal dengan Jabodetabek, yang merupakan kota-kota satelit yang mendukung persebaran dan pergerakan penduduk.
Soal operasi kependudukan, sejak ditinggalkan Bang Ali, para gubernur penerusnya pun tetap terus melanjutkan. Tujuannya tentu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk di Jakarta. Namun, Gubernur DKI Jakarta ke 17, Anies Baswedan belakangan ini justru membuat kebijakan baru yang bertolak belakang dari para pendahulunya. Alih-alih membatasi jumlah pendatang pasca Lebaran, Anies justru membuka lebar bagi warga yang hendak datang ke Jakarta untuk mencari nafkah.
“Jakarta adalah milik semua di Indonesia, tidak ada larangan bagi warga negara untuk tidak mendapatkan pekerjaan di manapun mereka berada. Itu prinsip dasar dalam bernegara dan Jakarta tidak dikecualikan dari itu,” ujar Anies.
Ide baru Anies pun langsung mendapat kritikan banyak pihak. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah mengatakan kebijakan Anies itu sama sekali tidak tepat, sebab Jakarta sudah terlalu padan dan akan semakin ramai jika tidak disaring. Dia menegaskan, penting bagi Pemerintah Provinsi untuk menekan laju urbanisasi, apalagi bagi orang-orang yang datang tanpa dibekali ketrampilan yang mumpuni.
“Orang datang ke Jakarta kalau bebas tanpa ada operasi Yustisi, ya Jakarta ini akan over load atau over capacity gitu,” kata Trubus. “Kalau mereka (yang datang) tidak punya ketrampilan, mereka nganggur mereka mau tinggal di mana? Bawah kolog jebatan, kolong layangan, bantaran sungai? Kan jadi menambah beban sosial dan beban DKI Jakarta.”
Kritik serupa juga datang dari kursi parlemen, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menilai Jakarta justru akan memiliki pekerjaan yang lebih besar jika nantinya banyak warga yang migrasi. Dia khawatir jika banyak warga luar daerah yang datang tanpa kompetensi akan berujung menjadi masalah sosial. Dalam hal ini, Pemprov DKI akan mengeluarkan uang untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.
“Jangan semua boleh gelontoran. Mau jadi apa Jakarta ini? Ini nanti kan ujung-ujungnya pengawasan Pemprov,” kata Gembong. “Ujung-ujungnya uang DKI juga yang mulangin.”
Macet Kronis
Selain masalah jumlah penduduk, ‘penyakit’ akut Jakarta adalah kemacetan. Sudah sejak lima dekade lalu, macet terus menghantui warga ibukota. Dari laporan Harian Kompas 5 Juli 1965 menyebut kecepatan mobil 16 km/jam butuh 45 menit untuk menempuh jarak yang 'hanya' 12 km. Berita tersebut menunjukan betapa kemacetan merupakan masalah klasik di Jakarta yang gejalanya sudah ada sejak 1965.
“Lalu lintas di Jakarta brengsek. Sayalah yang paling tidak puas terhadap keadaan itu,” ungkap Bang Ali seperti dikutip dari Historia.
Bang Ali menyadari kemacetan tersebut. Laju bertambahnya kendaraan di Jakarta terlampau pesat, pada 1967, kendaraan bermotor di ibukota mencapai setengah juta unit. Namun, usut punya usut, penyebab kemacetan pada saat itu adalah becak yang jumlahnya bisa mencapai 150.000 unit yang kini becak-becak tersebut harus rela jadi rumpon ikan karena dibuang Bang Ali ke Teluk Jakarta.
Sialnya, masalah macet juga tak kunjung selesai. Sampai sudah berusia nyari lima abad pun Jakarta masih tetap saja macet, bahkan masuk peringat 10 besar kota dengan tingat kemacetan tertinggi di dunia. Dikutip dari The TomTom Traffic Index mencatat Jakarta berada di peringkat ke 7 dari 403 kota yang paling macet di dunia, dengan level kemacetan mencapai 53 persen. Puncak kemacetan di Jakarta rata-rata berlangsung sore hari sekitar pukul 16:00 hingga 18:00 WIB, hampir semua ruas jalan tak terkecuali jalan tol pun tersendat akibat macet.
TomTom mencatat, pengendara di Jakarta harus menyiapkan waktu tambahan saat hendak berpegian. Jika diperkirakan lama perjalan selama satu jam, maka perlu menambah waktu 38 menit di pagi hari dan 52 menit pada sore hari.
Kini dengan diluncurkannya MRT dan LRT serta infrastruktur lainnya, tetap saja Jakarta terlihat semarawut dan membuat kewarasan warganya kerap hilang. Pertanyaannya, mau sampai kapan Jakarta sanggup menghadapi beban ini?