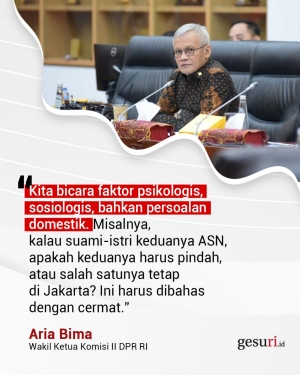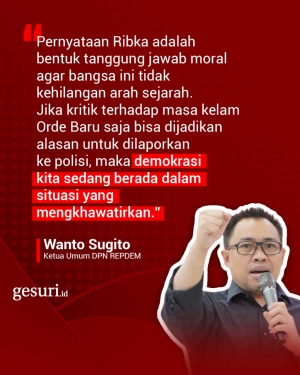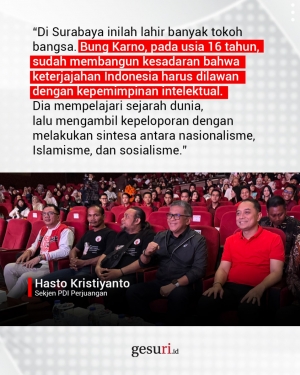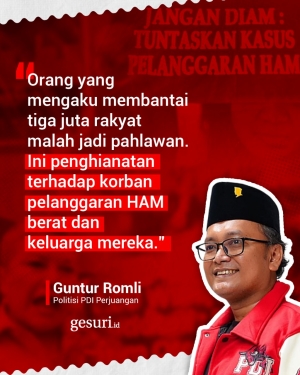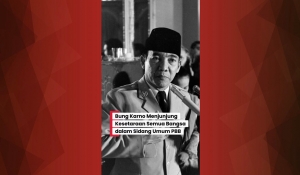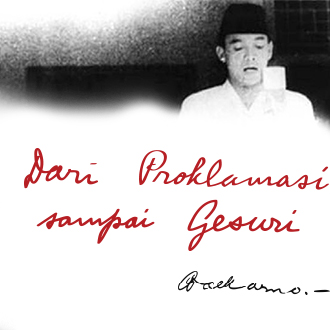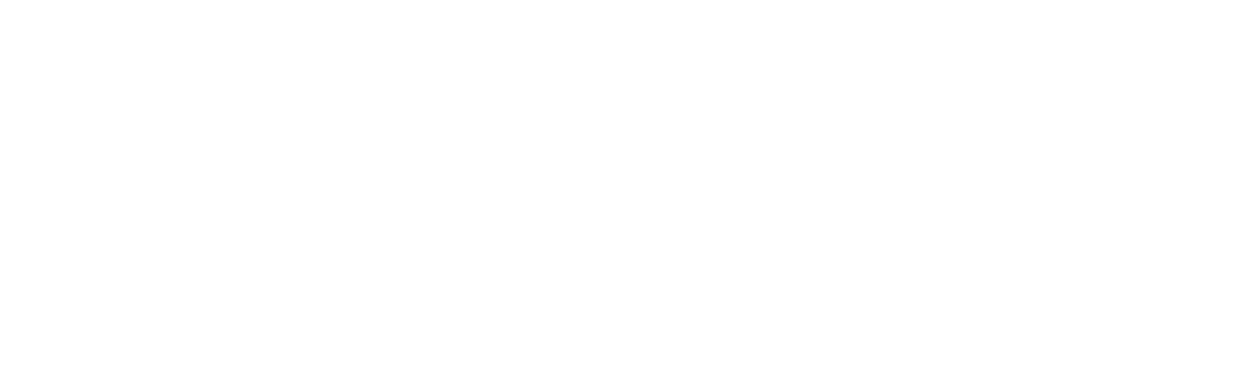Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, mengobarkan semangat kebangsaan dalam pidatonya pada acara Sekolah Duta Maritim Indonesia (DMI) Angkatan- 4, dalam rangka Munas III Aspeksindo dan Peringatan HUT RI ke – 80 di Ruang BAKN, DPR –RI Senayan, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.
Ia mendorong para Duta Maritim Indonesia untuk menjadi pionir dalam membangun masa depan bangsa. Mereka diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, berwirausaha, dan bekerja secara profesional di sektor kelautan dan perikanan, menjadi motor penggerak kesejahteraan dan kemakmuran nasional.
"Sebagai Duta Maritim Indonesia (DMI), tentu para DMI nantinya harus mampu berwirausaha (menciptakan lapangan kerja) atau bekerja secara professional di bidang (sektor-sektor) terkait dengan Kelautan (Maritim) atau Blue Economy untuk kesejahteraan diri dan kemajuan serta kemakmuran bangsa," ujarnya.
Mengusung tema “Pembangunan SDM Maritim Unggul Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045”, ia menegaskan pentingnya membangun wilayah pesisir dan kepulauan yang mandiri, sejahtera, dan berdaulat melalui ekonomi biru.
"Pertumbuhan ekonomi harus inklusif dan berkelanjutan, tidak hanya mengejar angka, tapi juga menyentuh seluruh masyarakat dan menjaga lingkungan," tegas Rokhmin Dahuri.
Beliau menekankan bahwa kemajuan bangsa tidak cukup hanya diukur dari angka pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang menyentuh aspek sosial, lingkungan, dan pemerataan manfaat di seluruh lapisan masyarakat.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat. Menurutnya, potensi besar Indonesia dengan konsep ekonomi biru, yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
“Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi negara yang maju, adil, makmur, dan berdaulat. Kuncinya adalah membangun wilayah yang mandiri dengan memanfaatkan kekayaan laut secara berkelanjutan melalui ekonomi biru,” ujarnya .
Melalui konsep ekonomi biru, Rokhmin yakin Indonesia bisa memimpin di kancah global, dengan SDM unggul, daerah maju merata, dan kesejahteraan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Rektor Universitas UMMI Bogor ini memaparkan, sejatinya Indonesia merupakan sedikit dari negara-negara di dunia yang memiliki potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap untuk menjadi negara-bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat.
Modal dasar pembangunan yang pertama adalah besarnya jumlah penduduk, yang tahun lalu mencapai 285,7 juta orang (BPS, 2021). Ini merupakan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia setelah China 1,4 milyar orang, India 1,2 milyar orang, dan Amerika Serikat 370 juta jiwa (PBB, 2021). Besarnya jumlah penduduk berarti Indonesia memiliki potensi pasar domestik yang luar biasa besar.
Selain itu, selama kurun waktu 2020 sampai 2032 Indonesia mengalami ‘Bonus Demografi’ (Demographic Devident), dimana jumlah penduduk usia produktif (15 – 64 tahun) melebihi jumlah penduduk berusia tidak produktif (Lampiran-1). Apabila pemerintah mampu mengelola ‘Bonus Demografi’ itu secara cerdas dan benar, meningkatkan kualitas (kapasitas inovasi, etos kerja, dan akhlak) SDM (Sumber Daya Manusia) nya.
"Dan menciptakan lapangan kerja yang mensejahterakan bagi seluruh penduduk usia kerja yang terus bertambah; maka ini bakal meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pertumbuhan ekonomi inklusif yang dapat mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan berkelanjutan,” terangnya
Dan sebaliknya, kata Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan - IPB University ini, bila pemerintah gagal memanfaatkan (to capitalize) ‘Bonus Demografi’ tersebut, maka Indonesia bakal terjebak sebagai negara berpendapatan menengah (middle-income trap), alias akan gagal menjadi bangsa yang maju, adil-makmur, dan berdaulat.
Modal dasar kedua adalah berupa kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) yang sangat besar, baik SDA terbarukan (seperti hutan, lahan pertanian, peternakan, perikanan, dan keanekaragaman hayati atau biodiversity) maupun SDA tidak terbarukan yang meliputi minyak dan gas, batubara, nikel, tembaga, emas, bauksit, bijih besi, pasir besi, mangan, mineral tanah jarang (rare earth), jenis mineral lainnya, dan bahan tambang.
Beragam jenis SDA itu tersebar di wilayah laut dan daratan, dari Sabang hingga Merauke, dan dari Pulau Miangas sampai P. Rote. Kekayaan SDA yang melimpah ini mestinya menjadikan Indonesia sebagai produsen (supplier) utama berbagai jenis komoditas dan produk di dunia.
Mulai dari produk pangan dan minuman, sandang (tekstil, garmen/pakaian, sepatu, dan jenis pakaian lainnya), perumahan dan bangunan, farmasi dan obat-obatan (kesehatan), teknologi dan manajemen pendidikan, elektronik, otomotif, mesin dan peralatan transportasi, teknologi informasi dan digital, bioteknologi sampai nanoteknologi.
Modal dasar ketiga adalah berupa posisi geopolitik dan geoekonomi yang sangat strategis. Indonesia yang terletak di antara Samudera Pasifik dan Hindia, dan di antara Benua Asia dan Australia, menempatkannya di jantung (hub) Rantai Pasok Global (Global Supply Chain) atau perdagangan global. Dimana, sekitar 45% dari seluruh komoditas, produk, dan barang yang diperdagangkan di dunia, dengan nilai rata-rata 15 trilyun dolar AS per tahun diangkut (ditransportasikan) oleh ribuan kapal melalui ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia) dan wilayah laut Indonesia lainnya (UNCTAD, 2018).
Posisi geoekonomi yang sangat strategis ini harusnya dijadikan peluang bagi Indonesia sebagai negara produsen dan pengekspor barang dan jasa (goods and services) utama di dunia, sehingga menghasilkan neraca perdagangan yang positip dan besar secara berkelanjutan.
"Sayangnya, justru sebaliknya, sejak 2010 hingga 2019 neraca perdagangan RI justru negatip terus. Artinya nilai total impor lebih besar ketimbang total nilai ekspor Indonesia. Dengan perkataan lain, bangsa Indonesia lebih sebagai bangsa konsumen dan pengimpor dari pada sebagai produsen, investor, dan pengekspor,” tegas Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan 2025 – 2030 itu.
Memang, lanjut Rokhmin Dahuri, tahun 2020 dan 2021 neraca perdagangan RI mengalami surplus. Tetapi, bukan karena meningkatnya aktivitas produksi, manufacturing, dan ekspor, tetapi lebih karena terpangkasnya kegiatan produksi, manufakturing, dan impor akibat pendemi covid-19 dan terganggunya rantai pasok global.
Modal dasar keempat adalah fakta empiris bahwa Indonesia merupakan pusat (‘pasar swalayan’) berbagai jenis bencana alam. Sekitar 70% total gunung berapi yang ada di dunia terdapat di Indonesia. Makanya, Indonesia dikenal sebagai ‘a ring of fire’.
Negara yang sering terkena gempa bumi dan letusan gunung berapi. Potensi bencana tsunami juga sangat besar, karena wilayah Nusantara merupakan pertemuan tiga lempeng bumi utama. Belum lagi bencana hidrometri, seperti banjir, tanah longsor, dan erosi.
Fakta empiris dan sejarah telah membuktikan semua negara-bangsa yang maju dan makmur adalah mereka yang para pemimpin dan rakyatnya punya persepsi sama, yakni adanya tantangan bersama (common challenges) yang mereka hadapi. Sehingga, mereka menjadi bangsa dengan kualitas SDM unggul, etos kerja unggul, dan berakhlak mulia.
"Nah, saya menduga karena alam Indonesia subur – makmur, bak zamrud di khatulistiwa, bak kolam susu, tongkat dan batu jadi tanaman. Dan, orangnya pun pada umumnya sangat baik, saling bantu-membantu, bergotong royong,” ujar Rokhmin Dahuri.
Maka, sambungnya, mayoritas orang Indonesia, baik para pemimpin maupun rakyatnya masih malas, kurang produktif dan inovatif, berbudaya instan, ‘tangan dibawah’, kurang mampu bekerjasama, saling iri dan dengki, dan karakter negatif lainnya.
“Jika, dugaan saya ini benar, maka bencana alam sungguh merupakan ‘hikmah’ dari Allah swt, agar bangsa (pemimpin dan rakyat) Indonesia terus meningkatkan kualitas, etos kerja, dan akhlaknya bagi kemajuan, kemakmuran, dan kedaulatan bangsa Indonesia,” katanya.
Meskipun modal dasar yang dimiliki bangsa Indonesia sedemikian besar, tetapi sudah 77 tahun merdeka Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah (lower-middle income country) dengan Pendapatan Nasional Kotor (Gross National Income) perkapita hanya sebesar 3.870 dolar AS (World Bank, 2021). Lebih dari itu, angka pengangguran, kemiskinan, ketimpangan kaya vs miskin, dan stunting pun masih sangat tinggi.
Menurutnya, banyak faktor yang menyebabkan Indonesia masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah, belum sebagai negara maju, sejahtera, dan berdaulat. Mulai belum adanya rencana pembangunan (Road Map, Blue Print) yang komprehensif dan benar serta diimplementasikan secara berkesinambungan sampai dengan masih rendahnya kualitas SDM, etos kerja, dan akhlak bangsa.
Kemudian, Menteri Kelautan dan Perikanan-RI 2001 – 2004 itu.menekankan potensi ekonomi sumber daya alam Indonesia yang sangat besar, terutama di sektor kelautan (ekonomi biru). Ia mengusulkan agar Indonesia memanfaatkan potensi ini untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, serta menjadi poros maritim dunia.
Maka jika dihitung dalam Rupiah, potensi pendapatan kotor dari SDA sebesar Rp. 20,655,696 triliun dan menghasilkan pendapatan bersih (untuk APBN) Rp. 7.279,49 triliun per tahun.
Saat kekayaan alam kita dikelola menurut Pasal 33 UUD 1945, maka anggaran APBN akan lebih dari 3 kali lipat APBN 2024 Rp 3.400. dan seharusnya dapat melunasi hutang negara hanya dalam waktu 3 tahun.
"Dengan potensi (modal dasar) pembangunan yang sangat besar dan lengkap diatas,sejatinya potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 10% per tahun," jelas Prof. Rokhmin Dahuri mengutip Mc. Kinsey, 2012; Goldman and Sach, 2020.
Lebih lanjut, Rokhmin Dahuri memaparkan, sejak merdeka pada 17 Agustus 1945, alhamdulillah bangsa Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan hampir di semua bidang kehidupan. “Contohnya, kalau pada 1945 – 1955 sekitar 70 persen rakyat Indonesia masih miskin, pada 1970 jumlah rakyat miskin menurun menjadi 60 persen,” ujarnya merujuk data BPS yang diolah oleh RD Institute (2023).
Selanjutnya, pada 2004 tingkat kemiskinan turun lagi menjadi 16 persen, tahun 2014 mejadi 12 persen, dan tahun 2019 tinggal 9,2 persen. Sayang, dampak dari pandemi Covid-19, pada 2023 tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 9,3% atau sekitar 26,4 juta orang.
“Menurut World Bank, ukuran ekonomi atau PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia saat ini mencapai 1,1 trilyun dolar AS atau terbesar ke-16 di dunia. Dari 200 negara anggota PBB, hanya 19 negara dengan PDB US$ > 1 triliun,” terangnya.
Lalu, Rokhmin Dahuri menjelaskan permasalahan & tantangan pembangunan Indonesia. Pertama. Pertumbuhan ekonomi rendah (<7% per tahun). Kedua, Pengangguran & Kemiskinan. Ketiga, Ketimpangan ekonomi terburuk ke-3 di dunia. Keempat, Disparitas pembangunan antar wilayah. Kelima, Fragmentasi sosial: Kadrun vs Cebong, dll. Keenam, Deindustrialisasi. Ketujuh, Kedaulatan pangan, farmasi, dan energy rendah. Kedelapan, Daya saing & IPM rendah. Kesembilan, Kerusakan, lingkungan & SDA. Kesepuluh, Volatilitas global (perubahan iklim, China vs AS, Industry 4.0).
Indonesia menduduki peringkat ke-3 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi tertinggi (terburuk) di dunia, Menurut laporan Credit Suisse’s Global Wealth Report 2019, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6% kue kemakmuran secara nasional, sementara 10% orang terkaya menguasai 74,1%
Kekayaan 4 orang terkaya (US$ 25 M = Rp 335 T) sama dengan total kekayaan 100 juta orang termiskin (40% penduduk) Indonesia. (Oxfam, 2017). L “Sekitar 0,2% penduduk terkaya Indonesia menguasai 66% total luas lahan nasional (KPA, 2015),” ungkapnya.
Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini < 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Hingga 2022, peringkat Global Innovation Index (GII) Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN. Hingga 2019, Global Entrepreneurship Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN. Hingga 2021, Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada diurutan ke-114 dari 191 negara, atau peringkat ke-5 di ASEAN. Indonesia peringkat ke-69 dari 81 negara tingkat literasi negara di dunia Riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.
Mengapa potensi pertumbuhan ekonomi lebih dari 10%? Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Laut, Universitas Bremen, Jerman tersebut memaparkan dalam 10 tahun terakhir (2015 – 2024) Indonesia hanya tumbuh rata-rata 5% per tahun, terutama melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan inovasi di berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEKS).
Ia menekankan pentingnya SDM yang unggul, kompeten, dan berakhlak mulia, serta peran ilmuwan dan ulama dalam membangun SDM tersebut. Selain itu, dibutuhkan juga upaya untuk menghasilkan penemuan dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan bangsa dan masyarakat global.
1. Iklim Investasi dan Ease of Doing Business kurang kondusif,sebagian besar Menteri, Dirjen, anggota DPR, dan Kepala Daerah ikut berbisnis (‘cawe-cawe’) dalam sektor yang mereka pimpin.
2. Kebanyakan Pejabat Negara dan Kepala Daerah kurang kompeten (profesional) dan ‘tidak the right person on the right place’
3. Stabilitas Politik-Ekonomi rendah: gonta-ganti kebijakan dan regulasi, kurang koordinasi dan sinkronisasi antar baik Kementerian/Lembaga maupun antar Pemerintah Pusat dan Pemda, premanisme Ormas, dll.
Akibatnya: sejak 2008 – 2024 relokasi sekitar 50 pabrik (industri manufaktur) milik MNCs asal AS, Eropa, dan Jepang dari China, tidak satu pun masuk ke Indonesia. Mereka memindahkannya Malaysia, Vietnam, Thailand, Pilipina, dan Kamboja. NVIDIA, LG, dan Apple batal investasi di Indonesia, dan hingga kini belum ada investor asing yang berinvestasi di IKN.
Rokhmin Dahuri menyebutkan ada beberapa faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal dibandingkan sejumlah bangsa lain.
“Penyebab ketertinggalan Indonesia itu ad faktor internal, ada pula faktor eksternal,” kata Ketua Dewan Pakar MPN (Masyarakat Perikanan Nusantara) itu.
Ia menyebutkan, faktor internal tersebut yaitu belum ada “Road Map Pembangunan Nasional yang Komprehensif, Tepat, dan Benar” yang dilaksanakan secara berkesinambungan; Kualitas SDM (knowledge, skills, expertise, kapasitas inovasi, etos kerja, nasionalisme, dan akhlak) masih rendah Sistem politik demokrasi liberal (Kapitalisme) yang sarat dengan politik uang dan kemunafikan, penegakkan hukum buruk, dan KKN massif; Belum ada pemimpin yang capable, negarawan, IMTAQ kokoh, dan ikhlas membangun bangsa.
Adapun faktor eksternal, katanya, antara lain Keserakahan bangsa-bangsa maju dan kapitalisme cenderung menjajah secara politik-ekonomi negara berkembang; Disrupsi Teknologi (AI, Drone, dll); Tensi Geopolitik makin meruncing: Perang Rusia vs Ukraina, Israel vs Palestina, persaingan AS vs China; Triple Ecological Crises (Pollution, Biodiversity Loss, and Global Warming; Nasionalisme rendah di kalangan pengusaha: (1) berubah dari industriawan menjadi importir, (2) nyimpan uang lebih 80% di LN, (3) gaji karyawan rendah, dan (4) R & D serta daya saing rendah (‘jago kandang’).
Hasil riset yang bertajuk World’s Most Literate Nations Ranked, dilakukan oleh Central Connecticut State University pada 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca Indeks Aktivitas Literasi Membaca (Indeks Alibaca) Nasional, termasuk di level rendah (37,32). Selanjutnya, 9 provinsi masuk dalam level sedang (26%); 24 provinsi masuk level rendah (71%); dan 1 provinsi masuk level sangat rendah (3%). Sedangkan Indeks Alibaca tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta (58,16).
Disisi lain, jelasnya, TFP (Total Productivity Factor) Indonesia menurun 50% sejak 2010, jauh di bawah negara-negara ASEAN (World Bank, 2023). Hingga 2022, peringkat GII Global Innovation Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 132 negara, atau ke-6 di ASEAN. Bahkan, pada 2018-2022, indeks daya saing Indonesia semakin menurun, hingga 2022 diurutan ke-44 dari 141 negara, atau peringkat ke-4 di ASEAN.
Jumlah wirausahawan Indonesia hanya mencapai 3,1 Persen dari Negara Asean lainnya. Sedangkan standar Bank Dunia, jumlah pengusaha minimal 7% dari jumlah penduduk. Hingga 2019, Global Entrepreneurship Index Indonesia berada diurutan ke-75 dari 137 negara atau peringkat ke-6 di ASEAN.
Sementara itu, implikasi dari Rendahnya Kualitas SDM, Kapasitas Riset, Kreativitas, Inovasi, dan Entrepreneurship adalah: Proporsi ekspor produk manufaktur berteknologi dan bernilai tambah tinggi bangsa Indonesia hanya 8,1%; selebihnya (91,9%) berupa komoditas (bahan mentah) atau SDA yang belum diolah. Sementara, Singapura mencapai 90%, Malaysia 52%, Vietnam 40%, dan Thailand 24% (UNCTAD dan UNDP, 2021).
Hasil ini menunjukkan bahwa masih banyak tantangan yang perlu diatasi dalam meningkatkan minat baca di Indonesia. Meningkatkan akses ke bahan bacaan yang berkualitas, memperbaiki infrastruktur perpustakaan, dan menggalakkan budaya membaca sejak dini bisa menjadi beberapa langkah yang diambil untuk memperbaiki situasi ini.
Selanjutnya, Rokhmin Dahuri menguraikan kondisi perekonomian terkini (2024) Indonesia, yaitu: Alarm Kinerja Industri Manufaktur, Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers’ Index = PMI) RI bulan Juni, yang dirilis S & P Global, mengalami penurunan, meskipun industri manufaktur masih dalam zona ekspansi (tercermin dari angka PMI yang masih diatas 50);
PMI bulan Juni sebesar 50,7, mendekati ambang batas menuju kontraksi industri manufaktur (PMI = 50). PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1; Angka PMI Juni merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022.
“Padahal, sektor industri manufaktur merupakan tulung punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI. Sektor ini juga banyak menyerap banyak tenaga kerja,” tandasnya.
Pada prinsipnya, Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menguraikan, ada 5 kecenderungan global (key global trends) yang mempengaruhi kehidupan dan peradaban manusia di abad-21, yakni: (1) jumlah penduduk dunia yang terus bertambah; (2) Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat); (3) Perubahan Iklim Global (Global Climate Change); (4) Dinamika Geopolitik; (5) Era Post-Truth.
Pertama adalah jumlah penduduk dunia yang terus bertambah. Pada 2011 jumlah penduduk dunia sebanyak 7 milyar orang, kini sekitar 7,9 milyar orang, tahun 2050 diperkirakan akan menjadi 9,7 milyar, dan pada 2100 akan mencapai 10,9 milyar jiwa (PBB, 2021).
Implikasinya tentu akan meningkatkan kebutuhan (demand) manusia akan bahan pangan, sandang, material untuk perumahan dan bangunan lainnya, obat-obatan (farmasi), jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, prasarana dan sarana transportasi dan komunikasi, jasa rekreasi dan pariwisata, dan kebutuhan manusia lainnya.
Implikasi selanjutnya adalah bahwa magnitude dan laju eksplorasi serta eksploitasi SDA dan jasa-jasa lingkungan (envrionmental services) baik di wilayah (ekosistem) daratan, lautan maupun udara akan semakin meningkat.
Kedua, era Industri 4.0 (Revolusi Industri Keempat) yang melahirkan inovasi teknologi dan non- teknologi baru yang mengakibatkan disrupsi hampir di semua sektor pembangunan dan aspek kehidupan manusia. Jenis-jenis teknologi baru yang lahir dan berubah super cepat di era Industri 4.0 berbasis pada kombinasi teknologi digital, fisika, material baru, dan biologi.
Antara lain adalah IoT (Internet of Things), AI (Artificial Intelligence), Blockchain, Robotics, Cloud Computing, Augmented Reality dan Virtual Reality (Metaverse), Big Data, Biotechnology, dan Nannotechnology (Schwab, 2016). Namun, hingga saat ini perkembangan industri teknologi digital masih bergerak pada sektor jasa dan distribusi saja (e-commerce dan e-government).
"Padahal seharusnya pemanfaatan berbagai teknologi industry-4.0 dapat meningkatkan dan mengefektifkan sektor eksplorasi, produksi, dan pengolahan (manufacturing) SDA untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang terus meningkat secara berkelanjutan,” terang Ketua Dewan Pakar Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) itu.
Ketiga, Perubahan Iklim Global (Global Climate Change) beserta segenap dampak negatipnya seperti gelombang panas, cuaca ekstrem, naiknya permukaan laut, pemasaman laut (ocean acidification), banjir, kebakaran lahan dan hutan, dan peledakan wabah penyakit; bukan hanya mengurangi kemampuan ekosistem bumi untuk menghasilkan bahan pangan, farmasi, energi, dan SDA lainnya. Tetapi, juga akan membuat kondisi lingkungan hidup yang tidak nyaman bahkan dapat mematikan kehidupan manusia (Sach, 2015; Al Gore, 2017).
Keempat, ketegangan geopolitik yang menjurus ke perang fisik (militer) seperti yang terjadi antara Rusia vs Ukraina. Ketegangan geopolitik yang lebih besar sebenarnya adalah antara AS serta para sekutunya (seperti Jepang, Australia, Inggris, dan Uni Eropa) vs China serta sekutunya (seperti Rusia, Korea Utara, dan Iran). Selain karena faktor ideologi, penyebab ketegangan geopolitik dan perang adalah perebutan wilayah dan SDA (resource war).
Sejumlah kawasan sangat rawan terjadinya perang, sperti Timur Tengah, Afrika, Laut China Selatan, Semenanjung Korea, dan Asia Timur. Invasi Rusia terhadap Ukraina telah memicu kenaikan harga pangan dan energi, inflasi yang tinggi, dan resesi ekonomi global. Akibat dari terganggunya produksi pupuk, pangan, dan energi serta rantai pasok global.
Kelima, Post-truth atau Paska Kebenaran adalah kondisi di mana fakta (kebenaran) tidak terlalu berpengaruh dalam membentuk opini publik dibanding emosi dan keyakinan personal (Hartono, 2018). Post-truth dianggap sebagai fenomena disrupsi dalam dunia politik yang secara besar-besaran diintensifkan oleh teknologi digital secara masif menjadi suatu prahara (Wera, 2020).
Pada era post-truth sekarang ini bangsa Indonesia perlu bersikap waspada karena hoaks politik dapat melemahkan ketahanan nasional, bahkan memecah belah NKRI, sehingga mengganggu proses pembangunan nasional yang sedang berjalan (Amilin, 2019).
Kelima kecenderungan global diatas mengakibatkan kehidupan dunia bersifat VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, and Ambiguous), bergejolak, tidak menentu, rumit, dan membingungkan (Radjou and Prabhu, 2015). Oleh sebab itu, sistem dan lembaga Pendidikan Tinggi harus mampu mendesain dan memberikan kapasitas kepada para mahasiswa nya dan bangsa Indonesia yang dapat mengelola atau mengatasi fenomena VUCA tersebut.
"Untuk mewujudkan Indonesia Emas pada 2045 dengan GNI per kapita sekitar 23.000 dolar AS dan PDB sebesar 7 trilyun dolar AS (ekonomi terbesar kelima di dunia), Indonesia seyogyanya mengimplementasikan Peta Jalan Pembangunan Bangsa," jelas Rokhmin Dahuri mengutip penelitian Bappenas.
Rokhmin Dahuri mengungkapkan bahwa Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan dalam sepuluh tahun terakhir, Indonesia menghadapi beberapa masalah serius dalam perekonomian, antara lain Indonesia.
Sejak sepuluh tahun terakhir Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Saat ini, Indonesia menghadapi beberapa tantangan ekonomi yang signifikan. Deflasi telah berlangsung selama lima bulan berturut-turut sejak Mei 2024, menunjukkan penurunan permintaan barang dan jasa.
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) semakin meningkat, yang berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Selain itu, kelas menengah mengalami penurunan, dan banyak warga negara yang terjerat utang PINJOL (Pinjaman Online) dan JUDOL (Judi Online).
Bahkan, sebutnya, utang negara yang semakin membengkak juga membebani anggaran pemerintah, mengurangi ruang fiskal untuk pembangunan bangsa.
"Kondisi ini memerlukan tindakan cepat dan efektif dari pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini dan memperbaiki situasi ekonomi," tegas yang juga Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu.
Selain itu, penurunan PMI (Purchasing Managers Index) Indonesia yang terjadi dari Mei hingga Juli 2024 menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam aktivitas manufaktur. PMI Juni itu menurun 1,4 dari PMI Mei sebesar 52,1. Kemudian, pada Juli berada pada 49,3 (zona kontraksi, PMI kurang 50), turun 1.4 poin dari bulan sebelumnya (Juni).
Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penurunan permintaan, stok barang jadi yang menurun, dan harga input yang terus naik. Hal ini mempengaruhi penyerapan tenaga kerja dan menyebabkan penumpukan pekerjaan menurun. Akibatnya, banyak pabrik mulai mengurangi produksinya atau bahkan menutup, yang pada akhirnya meningkatkan angka PHK..
Kontraksi aktivitas manufaktur terjadi setelah mampu bertahan di zona (level) ekspansi selama 34 bulan berturut-turut. Angka PMI Juli merupakan PMI terendah sejak Nopember 2022.
Padahal, sektor industri manufaktur (tekstil, Sritex) merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, yang menyumbangkan 18,7% PDB dan 72,24% total ekspor RI. Sektor ini juga menyerap banyak tenaga kerja Kontraksi Sektor Industri Manufaktur, khususnya TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) seperti PT. SRITEX dan elektronik, telah mengakibatkan PHK masih dan meluas. Sejak Covid-19) hingga sekarang gelombang PHK terus meningkat.
Pada 2022, PHK sebanyak 25.144 orang. Kemudian, pada 2023 PHK meningkat menjadi 64.855 orang, dan per Mei 2024, jumlah PHK mencapai 69.472 orang ( Kemenaker, 2024).
Akibatnya, dalam Sepuluh Tahun Terakhir, Penduduk Kelas Menengah Indonesia Semakin Rentan “Turun Kelas”. Jumlah penduduk kelas menengah Indonesia turun, dari 57,33 juta orang (21,45% total penduduk) pada 2019 menjadi 47,85 juta orang (17,13% total penduduk) pada 2024 (BPS, 2024).
Dalam 10 tahun terakhir, penduduk kelas menengah pun semakin rentan jatuh miskin. Hal ini terlihat dari data modus pengeluaran penduduk kelas menengah yang cenderung lebih dekat ke batas bawah kisaran (range) pengeluaran kelompok kelas menengah (Rp 2.040.262 – Rp 9.909.844 per bulan), yakni rata-rata Rp 2.056.494 per bulan.
"Dengan kata lain, selisih pengeluaran mayoritas kelas menengah dengan batas bawah pengeluaran kelas menengah (Rp 2.040.262 per bulan) hanya Rp 16.232 (BPS, 2024). Artinya: banyak sekali penduduk yang saat ini berstatus kelas menengah akan jatuh menjadi berstatus miskin, jika tidak ada kenaikan pendapatan (income) mereka," tandasnya.
Peningkatan utang pemerintah telah mengurangi ruang fiskal (APBN DAN APBD) dan mengurangi kapasitas pembangunan bangsa.Beban anggaran APBN untuk membayar cicilan pokok dan bunga utang Indonesia meningkat siginifikan dalam 10 tahun terakhir (Dua Periode Pemerintahan Presiden Jokowi).
Di kawasan Asia - Pasifik, negara-negara yang mengalami peningkatan beban bunga utang paling signifikan pasca Pandemi Covid-19 adalah Indonesia, Laos, Papua Nugini, dan Mongolia.
Beban pembayaran bunga utang (diluar cicilan pokok utang) dalam APBN 2024 sebesar Rp 497,3 trilyun. Angka ini nyaris menyamai dengan jumlah defisit APBN (proyeksi belanja negara yang akan dibiayai dengan utang) sebesar Rp 522,8 trilyun. Total utang RI saat ini Rp 8.444 trilyun (Kemenkeu, 2024).
Alokasi anggaran untuk membayar bunga utang itu merupakan yang kedua tertinggi dalam komponen belanja pemerintah pusat dalam APBN 2024. Yakni: anggaran Kesehatan Rp 187,5 trilyun, Perlinsos Rp 496,8 trilyun, Infrastruktur Rp 423,4 trilyun, dan Pendidikan Rp 665 trilyun.
Biaya yang diperlukan orang Indonesia untuk membeli makanan bergizi seimbang sebesar Rp 22.126/hari atau Rp 663.791/bulan. Harga tersebut berdasarkan pada standar komposisi gizi Healthy Diet Basket (HDB) (FAO, 2020).
"Atas dasar perhitungan tersebut; ada 183,7 Juta orang (68% total penduduk) yang tidak mampu memenuhi biaya tersebut," sebut Rokhmin Dahuri.
Rokhmin Dahuri menjelaskan, persyaratan dari Negara Middle-Income menjadi Negara Maju, Adil-Makmur dan Berdaulat, yaitu: Pertama, pertumbuhan ekonomi berkualitas rata-rata 7% per tahun selama 10 tahun. Kedua, I + E > K + Im. Ketiga, Koefisien Gini kurang 0,3 (inklusif). Keempat, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”
Rokhmin Dahuri menjabarkan peta jalan pembangunan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Selama 10 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi-RI stagnan di angka sekitar 5%, masih jauh dari potensi ekonomi-RI yang sesungguhnya, 8% – 10% per tahun (Mc. Kinsey, 2022; FE-UI, 2024).
“Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi sangat dominan bergantung pada konsumsi rumah tangga atau belanja masyarakat, sekitar 56%; dan ekspor bahan mentah,” terangnya mengutip Prof. Chatib Basri, 2024.
Sedangkan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mestinya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2019 – 2024 berkisar 6 – 7 persen per tahun; 2024 – 2029 tumbuh sekitar 8%; 2029 – 2034 tumbuh sekitar 7%; dan 2034 – 2045 timbuh sekitar 6,5% .
Angka pertumbuhan ekonomi ini bisa dicapai dengan kontribusi investasi terhadap PDB sebesar 41 – 48 persen. Sayangnya, kontribusi investasi terhadap PDB hingga kini baru mencapai 35% (Prof. Chatib Basri, 2024).
“Hal ini disebabkan karena ICOR Indonesia masih terlalu tinggi, alias tidak efisien (mahal) dan tidak efektif akibat birokrasi pemerintah yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme); dan Iklim Investasi yang kurang kondusif,” terangnya.
Selanjutnya, Dosen Kehormatan Mokpo National University Korea Selatan itu, memaparkan peta jalan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, yang menekankan pada optimalisasi peran ekonomi kelautan dan pembangunan sumber daya manusia berkualitas. Peta jalan ini juga menyoroti pentingnya transformasi ekonomi, peningkatan daya saing, dan penguatan peran kampus sebagai motor penggerak perubahan.
Pada tataran mikro: bangsa yang memiliki banyak Perusahaan (BUMN dan Swasta) dan Koperasi yang mampu menghasilkan barang dan jasa (goods
and services) yang berdaya saing tinggi (top quality, harga relatif murah, dan produksi teratur serta berkelanjutan) untuk memenuhi kebutuhan nasional
maupun ekspor secara berkelanjutan.
Pada tataran makro: pemerintah yang mampu menyediakan infrastruktur mumpuni, sarana produksi mencukupi dan relatif murah, SDM unggul, Iklim
Investasi dan Ease of Doing Business yang atraktif dan kondusif, dan kebijakan politik-ekonomi yang kondusif.
Pembangunan daya saing bangsa yang lebih murah, mudah, dan cepat berdasarkan pada comparative advantage bangsa. Bagi Indonesia, keunggulan komparatif adalah Agro-maritim.
Mengutip PBB, 2008, Prof. Rokhmin Dahuri menerangkan, “Transformasi Ekonomi Struktural meliputi: (1) realokasi faktor-faktor produktif dari pertanian tradisional ke pertanian modern, industri manufaktur, dan jasa; dan (2) realokasi faktor-faktor produktif tersebut ke dalam kegiatan sektor manufaktur dan jasa. Hal ini juga berarti pengalihan sumber daya (faktor produktif) dari sektor dengan produktivitas rendah ke sektor dengan produktivitas tinggi. Hal ini juga terkait dengan kapasitas negara untuk mendiversifikasi struktur produksi nasional untuk menghasilkan kegiatan ekonomi baru, memperkuat hubungan ekonomi dalam negeri, dan membangun kemampuan teknologi dan inovasi dalam negeri.”
Dalam kerangka perencanaan pembangunan, terdapat enam komponen strategis yang menjadi fokus utama dalam peta jalan menuju Kabupaten Asahan yang modern dan inklusif:
Manajemen adalah seni mencapai tujuan tertentu melalui kerja sama dengan orang lain. Sebagaimana ditegaskan oleh pakar manajemen Peter Drucker, kata Rokhmin Dahuri, manajemen adalah proses mencapai tujuan melalui kerja orang lain. Empat pilar manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian harus dijalankan secara utuh dan konsisten untuk memastikan pembangunan yang efektif.
Perencanaan menjadi titik awal dari proses ini. “Perencanaan adalah proses memetakan kegiatan masa depan untuk mencapai tujuan tertentu,” ujar Drucker dalam karyanya (2002). Hal ini relevan dengan situasi Kabupaten Asahan saat ini yang tengah membenahi arah pembangunan ke depan.