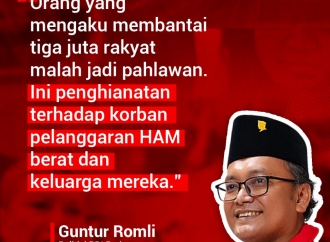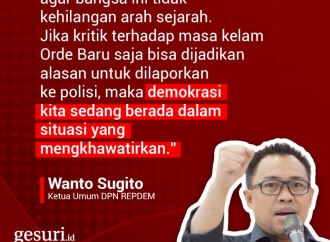Ciputat, Gesuri.id – Aktivis 98 sekaligus Direktur Lingkar Madani (LIMA), Ray Rangkuti, mengungkapkan pengalaman pribadinya yang getir di masa Orde Baru. Dalam diskusi publik bertajuk “Tolak Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto” yang digelar Forum Mahasiswa Ciputat (Formaci) di Tangerang Selatan, Sabtu (8/11), Ray menuturkan bagaimana kebijakan represif dan ketimpangan ekonomi di masa Soeharto membuat dirinya kesulitan menempuh pendidikan.
“Saya perih sekali mendengar orang yang membuat saya tidak bisa sekolah tepat waktu tiba-tiba mau dijadikan pahlawan,” ungkap Ray dengan nada getir di hadapan para mahasiswa. Ia menceritakan masa mudanya yang penuh kesulitan karena kondisi ekonomi yang timpang dan sistem sosial yang menindas rakyat kecil. “Soeharto membuat masa muda saya hilang. Saya tak bisa hidup layak, bahkan untuk kuliah pun penuh perjuangan,” tambahnya.
Ray bercerita bagaimana ia harus berjuang keras untuk bisa masuk dan menyelesaikan kuliah di UIN Jakarta. “Saya mendaftar paling lambat karena tidak punya uang. Biaya pendaftaran waktu itu hanya 25 ribu rupiah, tapi saya harus mencari ke sana ke mari. Akhirnya kuliah saya pun molor sembilan tahun,” tuturnya. Ia mengaku, beberapa kali terancam drop out karena tak mampu membayar uang kuliah.
Namun di balik kesulitan itu, tekad Ray untuk melawan ketidakadilan justru semakin kuat. “Saya mengalami sendiri penderitaan rakyat di masa Orde Baru, dan saya tidak ingin pengalaman itu berhenti di saya saja. Karena itulah saya turun ke jalan, ikut aksi melawan Soeharto,” katanya. Bagi Ray, perjuangan itu bukan sekadar pengetahuan, melainkan panggilan moral.
Dalam kesaksiannya, Ray juga mengenang masa-masa sulit sebagai mahasiswa yang harus bertahan hidup dengan makan nasi dan air garam. “Sering kali dua hari tidak makan, hanya minum air putih dicampur garam. Tapi saya harus tetap sekolah dan kuliah,” ujarnya. Kondisi ini, menurutnya, menggambarkan ketimpangan sosial yang sangat nyata di bawah rezim Orde Baru.
Ray kemudian menyinggung pengalaman ikut aksi di depan Mahkamah Agung saat menentang pemberhentian Hakim Agung Andoyo, yang kala itu dianggap berani menentang kehendak Soeharto. “Kami hanya berempat berdiri di depan Mahkamah Agung, sementara yang menjaga lebih dari 200 polisi. Tapi kami tetap maju. Itu nekat, tapi juga bentuk perlawanan moral,” ceritanya.
Menurut Ray, pengalaman itulah yang membuatnya tak habis pikir mengapa kini Soeharto justru diusulkan sebagai pahlawan nasional. “Bagi saya, yang membuat rakyat menderita, yang menindas, yang menutup pintu pendidikan dan keadilan, tak bisa disebut pahlawan. Kalau Soeharto jadi pahlawan, berarti kita melupakan air mata jutaan rakyat yang menjadi korban kebijakannya,” tegasnya.
Di akhir diskusi, Ray menyerukan agar generasi muda tidak mudah terbujuk romantisme Orde Baru. “Jangan biarkan politik memutihkan dosa masa lalu. Kita harus menjaga ingatan sejarah agar bangsa ini tidak kehilangan arah moralnya,” pungkasnya disambut tepuk tangan peserta.