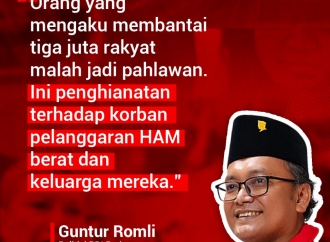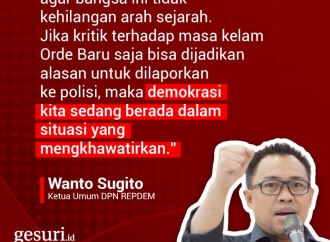Jakarta, Gesuri.id – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus Pendiri Islami.co, Savic Ali, menilai rezim Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto telah menjauhkan rakyat dari hak-hak dasarnya seperti pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Namun, di sisi lain, Soeharto berhasil menanamkan citra sebagai pemimpin yang membawa suasana “adem-ayem” bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Savic Ali dalam Diskusi Publik “Soeharto Bukan Pahlawan” yang digelar di Jakarta, Rabu (5/11). Ia menuturkan, dari pengalamannya tumbuh di desa, mayoritas masyarakat saat itu hidup dalam keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan.
“Di kampung saya, mungkin saya orang kedua yang bisa kuliah. Sebagian besar teman sebaya dan kakak-kakak saya tidak berkuliah karena tidak ada akses. Kalau sakit, orang tidak ke rumah sakit karena tidak punya uang, dan waktu itu belum ada BPJS. Jadi dirawat tradisional saja,” tutur Savic.
Savic menggambarkan masa Orde Baru sebagai periode di mana rakyat miskin dibiarkan dalam ketidaktahuan dan keterbelakangan. “Buku ‘Orang Miskin Dilarang Sakit’ itu sangat menggambarkan keadaan waktu itu,” ujarnya.
Namun yang menarik, lanjut Savic, sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa hidup di masa Soeharto “lebih enak”. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh psikologi sosial masyarakat yang mengutamakan harmoni ketimbang dinamika politik.
“Banyak orang, terutama di Jawa, menganggap zaman Soeharto itu enak karena adem. Padahal hak dasarnya dicabut — ekonomi, pendidikan, kesehatan. Tapi Soeharto menawarkan suasana tenang, tidak ribut. Itu ketenangan palsu,” ujarnya.
Savic menegaskan, rezim Soeharto tidak hanya menciptakan stabilitas semu, tetapi juga memperkuat monopoli kekuasaan sejak awal berkuasa. Ia menyebut, dukungan kuat dari Amerika Serikat pasca-1965 turut mengokohkan posisi Soeharto untuk berkuasa puluhan tahun ke depan.
“Soeharto memang sudah menyiapkan diri jadi penguasa jangka panjang. Undang-undang Penanaman Modal Asing pertama lahir di akhir 1960-an. Dia didukung Amerika dan membangun struktur kekuasaan lewat Golkar, ABRI, dan birokrasi,” jelas Savic.
Ia menyoroti Pemilu 1971 sebagai salah satu bukti praktik otoritarianisme Soeharto. Dalam pemilu pertama era Orde Baru itu, kata Savic, intimidasi merajalela bahkan terhadap tokoh-tokoh besar seperti Ketua Umum NU saat itu, KH Idham Chalid.
“Kiai Idham pernah bilang, Pemilu 1971 itu seperti disuruh tinju tapi kedua tangan diikat. Tapi ajaibnya, NU masih bisa bertahan dengan perolehan 18 persen suara, bahkan jumlah kursinya naik dibanding Pemilu 1955,” papar Savic.
Menurutnya, daya tahan politik NU di tengah tekanan itu terjadi karena kuatnya ikatan sosial dan tradisi pesantren yang menjadi fondasi kultural. “NU itu bukan cuma organisasi, tapi subkultur yang hidup. Ikatan sosialnya kuat, ada pengajian, tradisi kumpul, dan solidaritas yang luar biasa,” ujarnya.
Savic juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah memiliki nostalgia terhadap sosok Soeharto sebagaimana sebagian masyarakat yang masih menganggapnya sebagai figur ideal.
“Saya tidak pernah mengidolakan Soeharto. Saya bahkan tidak pernah menonton film G30S/PKI di bioskop seperti orang lain zaman itu. Mungkin itu yang menyelamatkan saya dari propaganda Orde Baru,” pungkasnya.
Melalui refleksi itu, Savic mengingatkan bahwa Orde Baru bukan masa keemasan, melainkan masa di mana rakyat dikendalikan dengan ketakutan dan ketenangan semu. “Soeharto bukan pahlawan, dia adalah simbol kekuasaan yang menindas dengan senyum dan stabilitas palsu,” tegasnya.