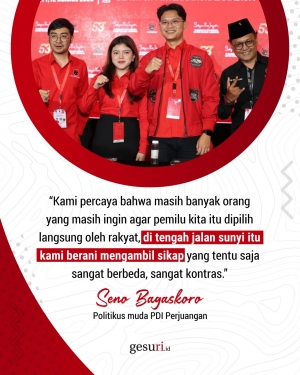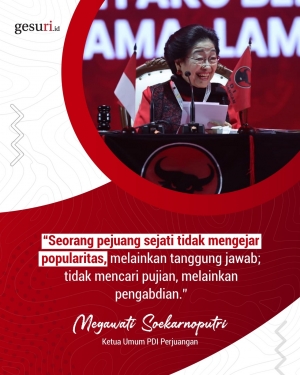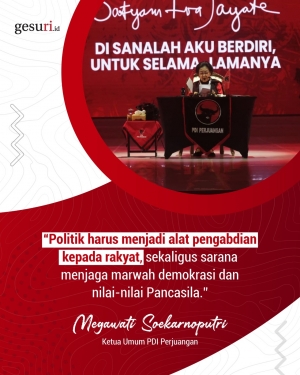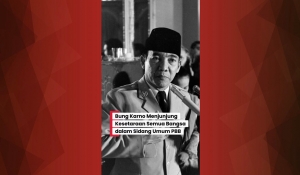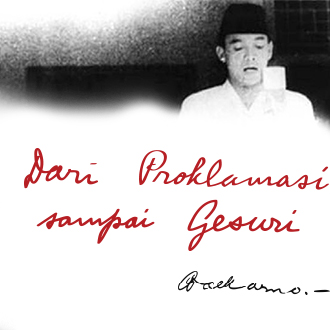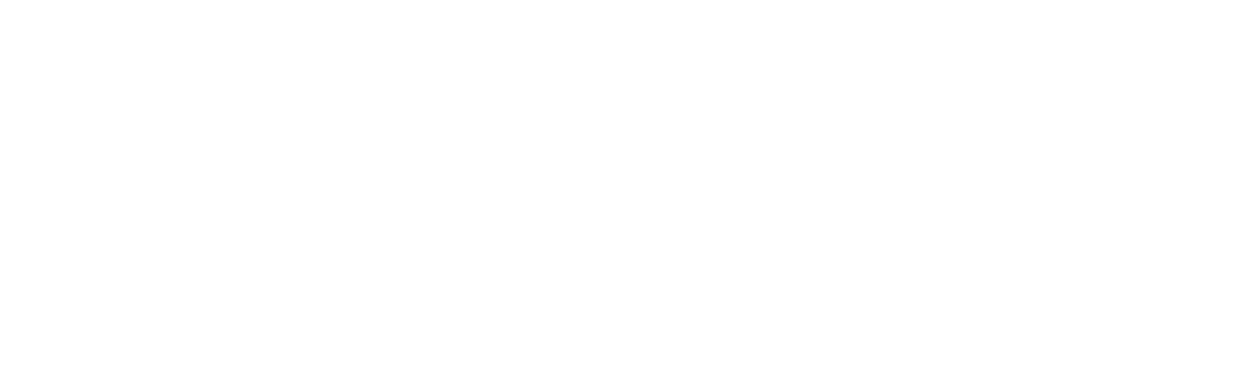Jakarta, Gesuri.id - Pidato Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Ibu Megawati Soekarnoputri, pada 11 Agustus 2025 di acara Serambi Pancasila dan Peluncuran Buku di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) kembali menggugah kesadaran publik.
Dalam pidatonya, Ketua Umum PDI Perjuangan menegaskan perlunya Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah konkret untuk memberantas praktik buzzer politik yang dinilai telah merusak ruang demokrasi nasional.
“Saya sudah bilang melalui seseorang supaya Pak Prabowo membuang itu namanya buzzer-buzzer yang hanya membuat perpecahan di antara kita sendiri, belum tentu faktanya aja. Silakan itu dimasukkan, saya ingin tahu. Saya tidak takut, karena ini adalah kebenaran, kebenaran yang hakiki,” ujarnya lantang.
“Kenapa? Padahal buzzer itu juga seringkali dimotivasi oleh uang. Kalian itu siapa? Kalau kalian yang dibuat seperti itu, lalu bagaimana?” lanjutnya.
Pernyataan tersebut bukan sekadar seruan moral, melainkan alarm keras atas terdistorsinya ruang publik digital.
Praktisi hukum yang merupakan anggota dari Badan Bantuan Hukum Advokasi & Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Triwiyono Susilo menyebut fenomena buzzer tidak bisa dipisahkan dari masalah mendasar demokrasi digital saat ini: anonimitas, identitas palsu, dan penyamaran sistemik di media sosial.
Dalam lanskap digital yang semakin tak terkendali, kehadiran akun anonim dan fiktif bukan sekadar fenomena teknis, melainkan telah berubah menjadi persoalan hukum, politik, dan sosial yang sangat serius. Hoaks, fitnah, ujaran kebencian, bahkan penipuan digital kerap bersumber dari akun-akun yang tidak dapat dipertanggungjawabkan identitasnya.
Ironisnya, opini yang mengalir deras di media sosial kini tidak selalu berasal dari suara rakyat yang sejati. Banyak narasi publik yang dibentuk, disetel, dan digiring oleh para buzzer bayaran demi kepentingan politik atau ekonomi jangka pendek.
Padahal, dalam doktrin demokrasi klasik dikenal adagium Latin yang agung: vox populi, vox Dei yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan.
Prinsip luhur ini hanya sah berlaku jika “suara rakyat” tersebut memang benar-benar berasal dari rakyat, bukan hasil manipulasi algoritma, robot akun palsu, atau tim digital berkepentingan.
Di sinilah letak urgensi kebijakan verifikasi identitas asli dalam media sosial. Pemerintah perlu segera mempertimbangkan regulasi yang mewajibkan verifikasi akun media sosial berbasis data kependudukan, seperti KTP atau Kartu Keluarga (KK).
Dengan kebijakan ini, ruang digital tidak lagi menjadi lahan bebas bagi penyamaran dan manipulasi. Pengguna akan lebih bertanggung jawab atas pernyataannya, dan pelaku penyebaran informasi menyesatkan pun lebih mudah dilacak dan ditindak secara hukum jika melakukan pelanggaran hukum.
Tentu, kritik terhadap wacana ini tidak terelakkan, terutama terkait potensi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Namun secara konstitusional, pijakan kebijakan ini cukup kuat.
Pasal 28E ayat (3) dan 28F UUD 1945 menjamin kebebasan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, tetapi Pasal 28J ayat (2) juga secara tegas memberi ruang pembatasan atas dasar ketertiban umum, nilai moral, serta perlindungan hak asasi orang lain.
Selama tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga ruang publik dari hoaks, fitnah, dan kejahatan digital, tanpa membungkam kritik yang konstruktif dan sah, maka kebijakan ini tetap berada dalam koridor konstitusional.
Dalam praktiknya, kebijakan ini membutuhkan revisi atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta aturan turunannya. Pemerintah juga harus memastikan perlindungan ketat terhadap data pribadi agar identitas pengguna tidak disalahgunakan atau bocor ke pihak yang tidak bertanggung jawab.
Selain itu, edukasi publik menjadi fondasi penting. Masyarakat harus memahami bahwa demokrasi yang sehat tidak bisa dibangun di atas fondasi anonimitas dan kebohongan yang tidak bertanggung jawab.
Selain memperbaiki etika komunikasi publik, kebijakan ini diyakini dapat meredam kejahatan digital seperti penipuan daring, investasi ilegal, hingga scam asmara yang banyak dijalankan melalui akun palsu.
Interaksi digital yang berbasis identitas jelas akan memberi rasa aman bagi warga sekaligus meningkatkan kualitas diskursus publik.
Pada akhirnya, usulan verifikasi identitas asli di media sosial bukan sekadar langkah administratif, melainkan bagian dari agenda besar politik hukum untuk menjaga integritas demokrasi Indonesia. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga soal siapa yang berbicara.
Bila yang mendominasi ruang publik adalah suara-suara palsu dari buzzer bayaran, maka adagium vox populi, vox Dei kehilangan maknanya.
Suara rakyat tidak boleh dicuri oleh mereka yang bekerja atas pesanan. Ruang digital adalah milik rakyat, bukan untuk mereka yang bersembunyi di balik identitas palsu.