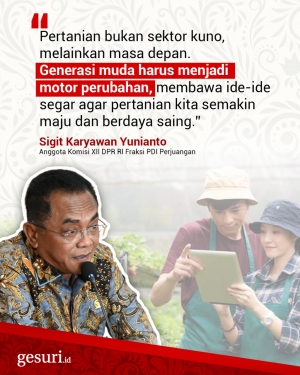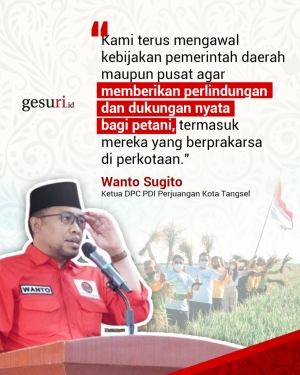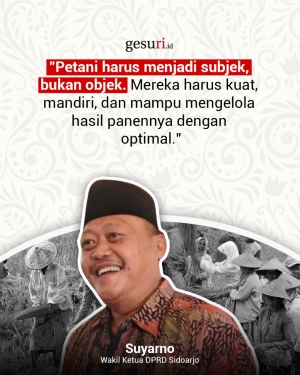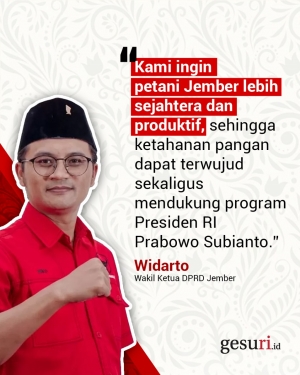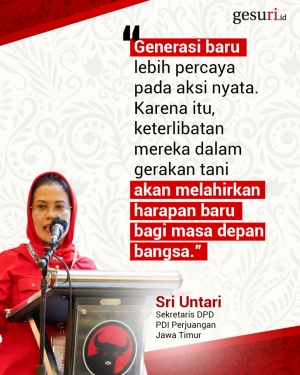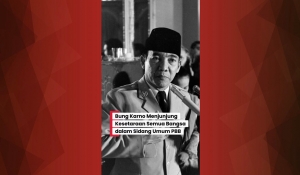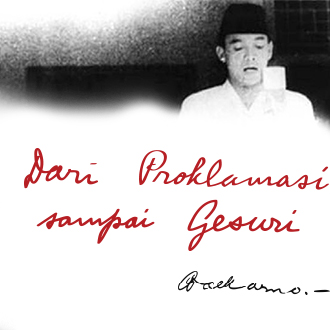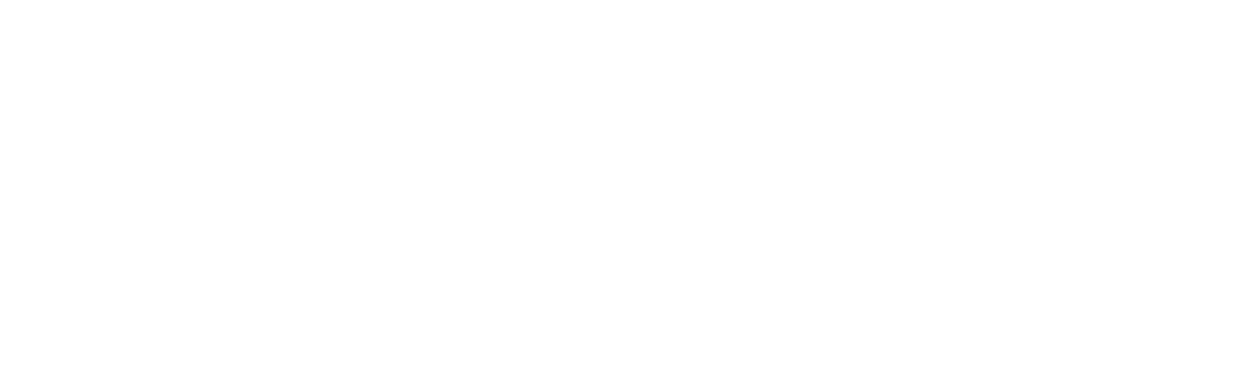Jakarta, Gesuri.id - DALAM suasana peringatan Sumpah Pemuda bulan Oktober ini, pantas kiranya kita mengenang salah satu tokoh penting di balik peristiwa bersejarah itu: Amir Sjarifuddin (1907–1948). Pada Kongres Pemuda 1928, Amir yang kala itu berusia 21 tahun menjabat sebagai bendahara panitia, mewakili organisasi Jong Bataks Bond.
Istilah “Sumpah Pemuda” memang belum dikenal waktu itu. Namun, peristiwa tersebut menjadi tonggak penyatuan semangat para pemuda dari berbagai daerah menuju satu cita-cita: Indonesia merdeka. Tragisnya, di akhir hayatnya, Amir mengalami nasib pahit akibat pilihan politiknya. Seperti halnya Sutan Sjahrir, Amir juga dikhianati oleh pendukungnya sendiri demi kepentingan politik kekuasaan yang gelap.
Dari Patriotisme Lokal ke Nasionalisme Indonesia
Pada masa Kongres Pemuda, Amir adalah sosok muda cerdas, orator ulung, pemain biola yang handal, namun juga dikenal emosional. Ia lahir sebagai seorang Muslim, kemudian berpindah menjadi penganut Kristen sekitar tahun 1935.
Sebagai pemimpin pemuda Batak, Amir bersama rekan-rekan seangkatannya sedang mengalami proses transformasi penting — dari semangat kedaerahan menuju nasionalisme Indonesia. Di dekade 1920-an, semangat kebangsaan mulai tumbuh kuat di kalangan pemuda yang bersekolah dan berorganisasi di Jakarta. Mereka perlahan meninggalkan identitas kesukuan dan melebur dalam satu tekad: Indonesia yang merdeka.
Kesadaran itu akhirnya berpuncak pada Sumpah Pemuda 1928, di mana Amir menjadi salah satu arsiteknya bersama tokoh-tokoh seperti Soegondo Djojopoespito (ketua kongres) dan Muhammad Yamin (sekretaris).
Fenomena serupa juga terjadi di Belanda melalui Perhimpunan Indonesia (PI), yang digerakkan oleh tokoh-tokoh seperti Soekiman Wirjosedjojo, Mohammad Hatta, Ali Sastroamidjojo, Sutan Sjahrir, Arnold Mononutu, Nazir Pamoentjak, Abdoel Madjid, dan Achmad Soebardjo. Mereka sedang mengucapkan “sayonara” pada kesetiaan etnisnya dan menatap lahirnya bangsa baru di garis khatulistiwa: Bangsa Indonesia.
Pergulatan Ideologi dan Awal Tragedi
Dalam dinamika zaman itu, tiga ideologi besar menjadi pemicu utama gerakan kebangsaan: Islamisme, Marxisme, dan Nasionalisme. Meski tampak berbeda, para pendukung ketiganya sejatinya sama-sama nasionalis, kecuali segelintir kaum Marxis yang masih menaruh kesetiaan kepada Uni Soviet.
Kapan tepatnya Amir menjadi seorang Marxis memang tidak diketahui pasti. Namun, besar kemungkinan pada awal 1930-an ia sudah terlibat dalam kegiatan PKI bawah tanah, meski secara formal aktif di organisasi Gerakan Rakyat Indonesia (Gerinda) yang didirikannya pada 1937.
Tahun 1940, ketika Perang Dunia II berkecamuk, Amir ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia diberi dua pilihan: dibuang ke Digul atau bekerja sama dengan Belanda. Amir memilih opsi kedua. Dengan modal 25 ribu franc, ia membangun jaringan bawah tanah untuk mempersiapkan perlawanan terhadap Jepang — yang kelak benar-benar datang dan menguasai Hindia Belanda pada Maret 1942.
Namun jaringan itu terbongkar. Amir ditangkap oleh Jepang dan pada 29 Februari 1944 dijatuhi hukuman mati. Berkat campur tangan Sukarno-Hatta, hukuman itu diubah menjadi penjara seumur hidup.
Tak sampai dua tahun kemudian, Jepang menyerah setelah bom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya — dan Amir kembali menghirup udara bebas.
Dari Menteri hingga Perdana Menteri
Pasca kemerdekaan, Amir yang dikenal berbakat dalam politik segera aktif mengurus pemerintahan baru. Namun situasi politik Indonesia kala itu sangat cair, penuh intrik dan perebutan pengaruh antar faksi.
Amir yang berpaham kiri sempat bersekutu dengan Sutan Sjahrir, namun hubungan itu tak bertahan lama. Setelah Kabinet Sjahrir II jatuh, pada Juli 1947 Amir menggantikannya sebagai Perdana Menteri, setelah sebelumnya menjabat Menteri Pertahanan.
Langkah-langkah Amir yang dianggap terlalu condong ke kiri membuat Masyumi dan PNI menarik diri dari kabinet. Posisinya pun melemah. Sebagai Menteri Pertahanan, Amir membentuk “tentara rakyat” di luar struktur resmi TRI/TNI dan bahkan memecat Jenderal Soedirman serta Jenderal Oerip Soemohardjo.
Ketegangan politik memuncak. Kabinet Amir jatuh pada 23 Januari 1948 dan digantikan oleh Kabinet Hatta. Soedirman dan Oerip kemudian dipulihkan untuk memimpin TNI.
Akhir Tragis di Madiun
Kekalahan kelompok kiri membuat mereka kehilangan arah. Oposisi terhadap Hatta berubah menjadi pemberontakan PKI di Madiun pada 18 September 1948, dipimpin oleh Muso, tokoh veteran PKI 1926/1927. Amir turut terlibat dalam gerakan ini.
Hatta merespons tegas. Pasukan Divisi Siliwangi dikerahkan dan dalam waktu singkat pemberontakan berhasil ditumpas. Amir ditangkap di persembunyiannya di Desa Klambu, Purwodadi, pada 29 November 1948 dalam kondisi sakit disentri.
Ia sempat dibawa ke Kudus, lalu ke Yogyakarta, sebelum akhirnya dikirim ke Solo atas perintah Jenderal Gatot Soebroto, gubernur militer kala itu. Tengah malam, 19 Desember 1948, Amir bersama 10 tawanan lainnya dieksekusi di Desa Ngalihan, Karanganyar, Surakarta.
Amir Sjarifuddin — salah seorang otak Sumpah Pemuda, mantan Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri — menutup hidupnya secara tragis, ditembak mati oleh bangsanya sendiri.
Sengketa politik kekuasaan memang sering menelan korban. Amir hanyalah salah satu di antaranya.
Disadur dan diolah lagi dari kolom “Resonansi” Harian Republika, edisi 30 Oktober 2007.
Ahmad Syafii Maarif (1935–2022) adalah cendekiawan dan kolumnis Republika
*Tulisan ini merupakan rangkaian kegiatan Merah Muda Fest 2025 untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda 2025 yang akan diselenggarakan Selasa 28 Oktober 2025 di Sekolah Partai DPP PDI Perjuangan Jakarta dan Sabtu 1 November 2025 di GOR Among Rogo Yogyakarta.