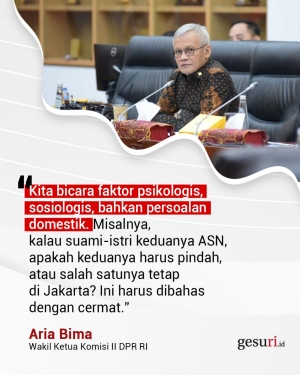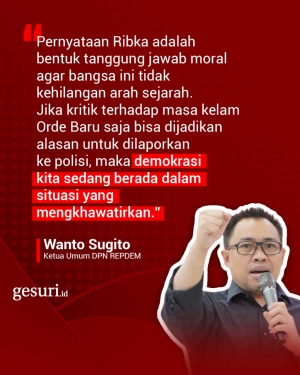Jakarta, Gesuri.id - Wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali menguat. Usulan ini, yang digaungkan oleh koalisi pendukung pemerintah, diklaim sebagai upaya efisiensi anggaran dan perbaikan sistem politik.
Namun, jika ditelaah lebih dalam, gagasan ini justru berpotensi menggerus substansi demokrasi Indonesia dan merampas hak konstitusional rakyat. Di tengah konsolidasi demokrasi yang masih terus berlangsung, wacana ini menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan rakyat yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar selama lebih dari dua dekade terakhir.
Pertama, Pilkada langsung adalah buah perjuangan reformasi yang diraih dengan darah dan air mata. Setelah puluhan tahun hidup dalam bayang-bayang otoritarianisme Orde Baru, rakyat Indonesia akhirnya memperoleh hak untuk menentukan sendiri pemimpin daerahnya melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Menghapus sistem ini sama artinya dengan menghapus salah satu capaian paling fundamental dari gerakan reformasi 1998. Para mahasiswa yang gugur di Trisakti dan Semanggi, para aktivis yang diasingkan dan dipenjarakan, serta jutaan rakyat yang turun ke jalan, semuanya berjuang agar rakyat Indonesia memiliki hak memilih pemimpinnya secara langsung. Sungguh ironis jika hak yang diperjuangkan dengan begitu mahal justru diserahkan kepada segelintir elite di DPRD, seolah-olah perjuangan reformasi tidak bermakna apa-apa.
Baca: Ganjar Tekankan Kepemimpinan Strategis
Kedua, Indonesia memiliki rekam jejak kelam ketika Pilkada dilakukan oleh DPRD. Pada masa Orde Baru, intervensi kekuasaan pusat terhadap pemilihan kepala daerah sangat kuat melalui mekanisme “penjaringan” yang dikendalikan Golkar dan militer. Praktik transaksional dan politik uang justru lebih mudah terjadi dalam ruang tertutup parlemen ketimbang dalam pemilihan langsung yang melibatkan jutaan mata rakyat sebagai pengawas. Cukup bernegosiasi dengan puluhan anggota DPRD untuk mengamankan kursi kepala daerah, berbeda dengan Pilkada langsung yang mengharuskan calon meyakinkan jutaan pemilih. Sejarah mencatat bagaimana kepala daerah pada era Orde Baru lebih loyal kepada pusat ketimbang kepada rakyat yang seharusnya mereka layani. Kekhawatiran akan hadirnya “cawe-cawe” pihak tertentu bukan tanpa dasar historis di mana pengalaman pahit telah mengajarkan bahwa konsentrasi kekuasaan pemilihan di tangan segelintir orang membuka ruang lebih besar bagi manipulasi dan kolusi.
Ketiga, legitimasi kepemimpinan daerah menuntut dukungan langsung dari rakyat. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki modal politik yang kuat untuk menjalankan kebijakannya secara independen. Mereka bertanggung jawab langsung kepada konstituen, bukan kepada oligarki partai atau kepentingan segelintir elite. Sistem ini memastikan bahwa pemimpin daerah benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat yang memilihnya, bukan untuk kepentingan elite yang mengangkatnya. Lebih dari itu, Pilkada langsung telah melahirkan banyak pemimpin inovatif yang berani mengambil kebijakan pro-rakyat karena merasa memiliki mandat langsung dari masyarakat. Tri Rismaharini di Surabaya dengan program kebersihan dan ruang terbuka hijau, Ridwan Kamil di Bandung dengan inovasi smart city, dan Ganjar Pranowo di Jawa Tengah dengan transparansi birokrasi adalah contoh nyata bagaimana Pilkada langsung mampu menghasilkan pemimpin yang responsif terhadap aspirasi warga.
Keempat, data empiris menunjukkan bahwa rakyat Indonesia secara konsisten menolak gagasan Pilkada tidak langsung. Survei Saiful Munjani Research and Consulting (SMRC) yang dilakukan berulang kali sejak 2020 hingga 2023 menunjukkan bahwa sekitar 80 persen responden menolak usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD. Hanya sekitar 10-20 persen yang menyetujui. Temuan serupa juga dikonfirmasi oleh berbagai lembaga survei lainnya seperti Litbang Kompas dan Indo Barometer. Angka ini konsisten dari waktu ke waktu dan lintas demografi, baik di perkotaan maupun pedesaan, di Jawa maupun luar Jawa, menandakan bahwa preferensi rakyat terhadap Pilkada langsung bukan sekadar sentimen sesaat, melainkan sikap politik yang mengakar dalam kesadaran kolektif bangsa. Dalam konteks demokrasi, mengabaikan suara mayoritas yang begitu dominan adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat itu sendiri.
Kelima, argumen efisiensi anggaran yang kerap dilontarkan pendukung Pilkada tidak langsung perlu dikritisi secara tajam. Demokrasi memang membutuhkan biaya, tetapi biaya tersebut adalah investasi untuk menjaga kedaulatan rakyat dan memastikan akuntabilitas pemerintahan. Jika efisiensi menjadi alasan utama, maka solusinya adalah memperbaiki tata kelola pemilu seperti penyederhanaan logistik, penggunaan teknologi informasi, konsolidasi penyelenggaraan pemilu, dan pelaksanaan Pilkada serentak, bukan menghapus hak pilih rakyat. Mengorbankan substansi demokrasi demi efisiensi adalah logika yang terbalik dan berbahaya. Lagipula, jika dihitung secara komprehensif, biaya politik uang dalam Pilkada melalui DPRD yang tertutup berpotensi jauh lebih besar daripada biaya penyelenggaraan Pilkada langsung yang diawasi publik secara terbuka.
Baca: Ganjar-Risma Pimpin Aksi Kemanusiaan untuk Korban Bencana
Keenam, konstitusi Indonesia mengamanatkan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis melalui pemilu yang jujur dan adil. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 hasil amandemen menyebutkan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.” Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga telah menegaskan bahwa frasa “dipilih secara demokratis” harus dimaknai sebagai pemilihan langsung oleh rakyat. Suasana kebatinan para perumus amandemen ketika menuliskan ketentuan ini adalah memberikan ruang seluas-luasnya bagi partisipasi rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Mengubah sistem ini tanpa mempertimbangkan aspirasi rakyat adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat konstitusi dan cita-cita reformasi yang telah dicanangkan.
Maka, ketika wacana Pilkada tidak langsung kembali digulirkan, sikap yang paling masuk akal adalah menolak dengan tegas. Bukan karena alergi terhadap perubahan, melainkan karena perubahan yang diusulkan justru akan membawa kemunduran demokrasi. Pilkada langsung harus dipertahankan sebagai benteng terakhir kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Sejarah telah membuktikan bahwa sistem ini, meskipun tidak sempurna, jauh lebih baik dalam menjamin akuntabilitas pemimpin daerah kepada rakyatnya. Perbaikan yang diperlukan adalah menyempurnakan mekanisme Pilkada langsung, bukan menghapusnya sama sekali.
Pada akhirnya, yang terpenting adalah memastikan bahwa kepala daerah mampu menghasilkan keputusan politik yang mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan, dan menghapus kesenjangan sosial. Namun, kemampuan tersebut akan lebih terjamin jika pemimpin daerah memiliki legitimasi kuat dari rakyat, legitimasi yang hanya bisa diperoleh melalui pemilihan langsung. Pilkada langsung bukan sekadar prosedur teknis pemilihan, melainkan perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat yang tidak boleh dirampas oleh siapa pun, dengan dalih apa pun. Mari kita jaga bersama warisan reformasi ini untuk generasi mendatang.