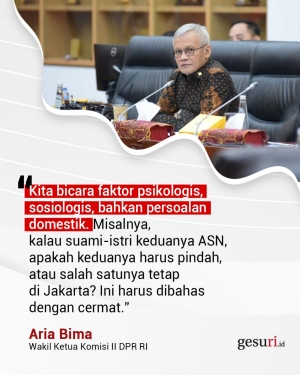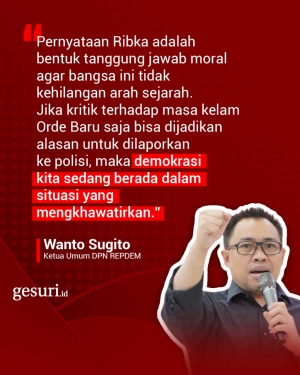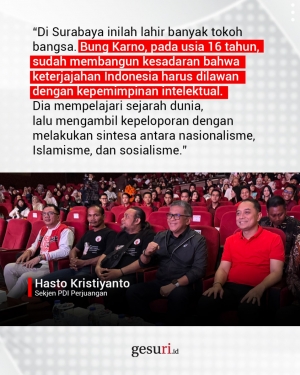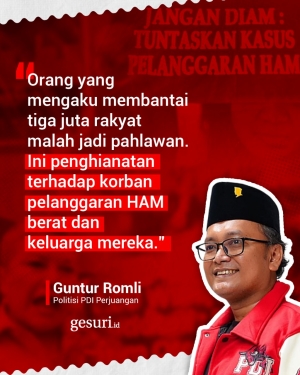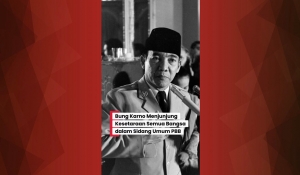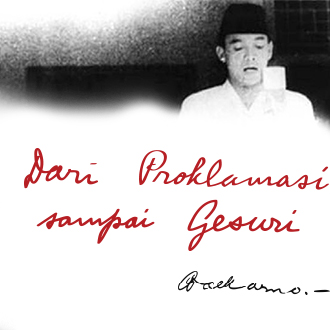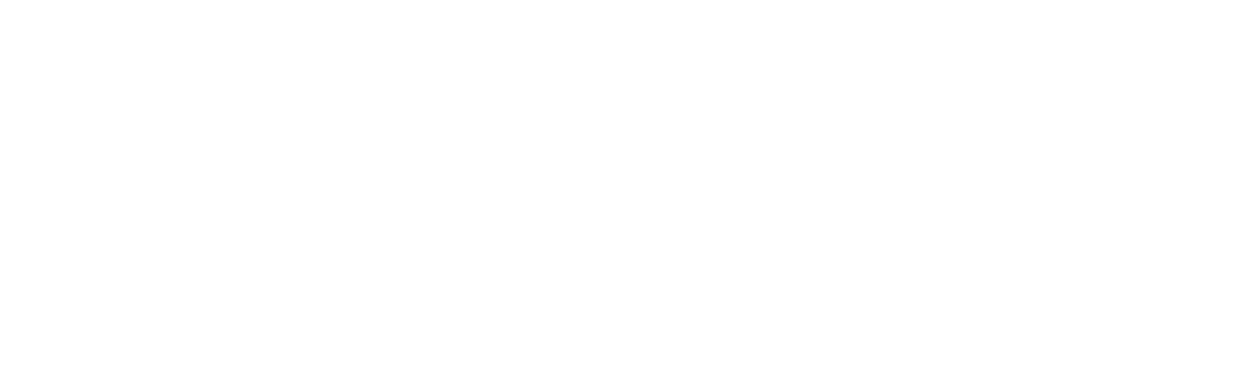Jakarta, Gesuri.id - Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menekankan pentingnya harmonisasi antara perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan sektor pariwisata sebagai strategi utama memperkuat ekonomi pesisir dan kesejahteraan masyarakat Pangandaran, Ciamis, Jawa Barat.
Hal itu disampaikannya dalam Round Table Discussion “Strategi Pengembangan Akuakultur dan Kelayakan Budidaya Ikan Laut Pangandaran Menuju Indonesia Emas 2045” di ajang ILDEX Indonesia, ICE BSD City, Rabu (17/9).
Menurut Rektor Universitas UMMI Bogor itu, sektor kelautan dan perikanan Pangandaran memiliki potensi besar jika dikelola secara terintegrasi, berbasis tata ruang laut (RZWP3K), dan berkelanjutan.
Ia menegaskan pentingnya menerapkan praktik budidaya terbaik (Best Aquaculture Practices), memanfaatkan komoditas unggulan seperti kerapu, barramundi, lobster, dan rumput laut, serta mendorong ekowisata bahari berbasis KJA (Keramba Jaring Apung) modern yang juga menjadi atraksi wisata.
“Sea farming bisa jadi objek wisata. Wisatawan bisa mancing, kasih makan ikan, hingga belajar langsung proses budidaya laut. Ini bisa meningkatkan nilai tambah sekaligus menjaga ekosistem,” ujar Rokhmin dalam tema "Mengharmoniskan Pembangunan Perikanan Budidaya, Pariwisata, Dan
Perikanan Tangkap Di Laut Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat Pangandaran Berkelanjutan".
Kemudian, Rokhmin juga menyoroti pentingnya menjaga kebersihan laut dari kegiatan wisata dan nelayan, serta mendorong sinergi multipihak melalui kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Swasta, Akademisi, Masyarakat, dan Media).
“Dengan sinergi yang kuat dan pengelolaan yang tepat, Pangandaran bisa menjadi model nasional dalam pembangunan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa landasan kebijakan dan regulasi sektor kelautan dan perikanan harus berpusat pada ekonomi biru (Blue Economy) untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada potensi nilai ekonomi sumber daya alam kelautan dan perikanan seperti akuakultur dan keanekaragaman hayati.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus didukung dengan perencanaan pembangunan yang matang, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan elemen masyarakat.
Pertama, Pancasila, dan UUD 1945 yang di dalam Pembukaannya menyatakan bahwa tujuan NKRI: (1) melindungi segenap tumpah darah Indonesia, (2) mencerdaskan kehidupan bangsa, (3) memajukan kesejahteraan umum, dan (4) turut menjaga ketertiban dan kedamaian dunia.
Kedua, Berbasis ilmu pengetahuan (science-based planning and decision making processes). Ketiga, Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development).
Keempat, TUSI (Tugas dan fungsi) KKP: (1) mengatasi permasalahan internal sektor KP; (2) berkontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan bangsa;
dan (3) mendayagunakan seluruh potensi pembangunan KP secara produktif, efisien, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan guna mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Prof. Rokhmin Dahuri mengusulkan paradigma (model) pembangunan Berdasarkan Ekologi Dan Ekonomi, yaitu Deep Environmentalist (Pencinta Lingkungan yang Mendalam) yang menekankan, 1. Zero economic growth (pertumbuhan ekonomi nol atau nol pertumbuhan ekonomi), 2. No-take zones (zona larangan mengambil atau zona terlarang penangkapan), 3. Low utilization of natural resources and environmental services (pemanfaatan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang rendah), 4. Zero population growth (nol pertumbuhan penduduk)
Pembangunan Berkelanjutan: 1. Pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kebutuhan generasi mendatang. (WCED, 1987), 2. Pembangunan untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bagi seluruh manusia secara adil, ramah lingkungan, tidak melampaui daya dukung lingkungan, dan berkelanjutan.
Mania Pertumbuhan (Kapitalisme) 1. Pertumbuhan tanpa batas, 2. Maksimalisasi keuntungan, 3. Rak, akumulasi kekayaan, 4. Kolonisasi, 5. Kaya raya, bersih-bersih nanti, 6. Sejauh “Jangan di halaman belakang rumah, Anda bisa mencemari”
Dalam pemaparannya, Prof. Rokhmin Dahuri melihat potensi besar akuakultur sebagai "game-changer" untuk pembangunan Indonesia Emas 2045, yang dapat menjadi fondasi ketahanan pangan dan kunci kemakmuran nasional. Beliau menekankan pentingnya akuakultur sebagai pilar utama pembangunan agromaritim yang inklusif dan berkelanjutan.
"Kalau dikelola serius, akuakultur bisa jadi game changer Indonesia 2045. Bukan sekadar sektor ekonomi, tapi landasan transformasi sosial dan lingkungan,” tandasnya.
Pertama, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, yang 75% wilayahnya berupa laut dan 28% wilayah daratnya berupa ekosistem perairan tawar (sungai, danau, bendungan, dan perairan rawa); potensi produksi lestari perikanan budidaya (aquaculture) – RI sangat besar, sekitar 100,06 juta ton/tahun, dan pada 2023 baru dimanfaatkan (produksi) sebesar 15,36 juta ton (15,36%).
Peluang untuk pengembangan perikanan budidaya untuk menghasilkan komoditas/produk konvensional (finfish, crustacean, mollusk, dan rumput laut) masih terbuka sangat lebar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan pangan.
Kedua, lebih dari itu, aquaculture bukan hanya menghasilkan komoditas/produk konvensional, tetapi juga komoditas/produk nonkonvensional, seperti bahan baku untuk industri functional food and beverages, farmasi, kosmetik, bioplastic, pupuk organik, cat, biofuel, bahkan food crop dengan genome editing → Sumber pertumbuhan ekonomi baru, kedaulatan energi dan produk lainnya.
Ketiga, investasi dan bisnis aquaculture banyak menyerap tenaga kerja (labor-intensive), setiap 1% pertumbuhan ekonomi menciptakan 450.000 orang tenaga kerja untuk mengatasi masalah pengangguran.
Keempat, pada umumnya investasi dan bisnis aquaculture sangat menguntungkan (lucrative) untuk mengatasi kemiskinan. Kelima, modal investasi dan usaha aquaculture relatif tidak terlalu besar, dan bukan ‘a rocket science’, sehingga kebanyakan rakyat mampu mengerjakannya dalam engatasi masalah ketimpangan kaya vs miskin (economic inequality).
Keenam, sebagian besar investasi dan usaha aquaculture berlangsung di wilayah perdesaan, pesisir, laut, dan luar Jawa untuk mengatasi masalah kronis disparitas pembangunan antar wilayah,l.
Ketujuh. Aquaculture ialah sustainable resource (sector), sehingga menjadi bagian integral dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development).
Rokhmin mendorong pengembangan pangan biru (pangan dari laut) dan menegaskan bahwa potensi produksi akuakultur dan maritim Indonesia yang mencapai 115 juta ton per tahun, harus dimanfaatkan secara optimal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas.
Ia juga menyoroti pentingnya membangun industri akuakultur terpadu, mulai dari budidaya, pengolahan, logistik hingga pemasaran, agar ekonomi lokal tumbuh dengan efek berganda. Menurutnya, pelabuhan perikanan harus berevolusi dari sekadar tempat tambat-labuh menjadi kawasan industri modern.
“Selama ini kita terlalu sentralistik. Daerah seperti Pangandaran harus diberi kewenangan lebih luas untuk mengelola sumber dayanya. Investasi harus masuk, industri harus tumbuh,” tegasnya.
Ketua Umum MAI (Masyarakat Akuakultur Indonesia) ini menegaskan bahwa sektor kelautan dan perikanan bukan hanya soal pangan, tetapi kunci untuk mengentaskan kemiskinan, mengurangi pengangguran, memperbaiki gizi, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Saatnya perikanan jadi pilar utama pembangunan maritim Indonesia. Kalau ini kita jalankan dengan niat serius dan penuh keadilan, Indonesia Emas 2045 bukan lagi angan-angan,” ucapnya.
Dalam paparan visionernya, Rokhmin Dahuri menyebut perlunya transformasi pelabuhan perikanan menjadi kawasan industri terpadu.
Ia juga mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan kewenangan lebih kepada kabupaten dalam pengelolaan sumber daya laut.
"Dengan pendekatan industri, kita bisa ciptakan efek berganda bagi ekonomi lokal,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan sektor perikanan sebagai pilar utama pembangunan maritim Indonesia.
"Jika dikelola serius dan berkeadilan, sektor ini mampu atasi pengangguran, tingkatkan gizi rakyat, dan dorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan," tegasnya.
Rokhmin Dahuri melihat peluang besar dalam industri offshore aquaculture (budidaya laut lepas) di Pangandaran. Karena potensi sumber daya laut Indonesia yang melimpah dan kebutuhan untuk memanfaatkan laut sebagai masa depan ekonomi negara, sesuai dengan konsep ekonomi biru (blue economy) yang berkelanjutan.
"Pengembangan ini harus didukung oleh penataan tata ruang yang baik, teknologi revolusi industri 4.0, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan nelayan agar manfaatnya merata," ujar Menteri Kelautan dan Perikanan 2001-2004 itu.
1. Sea farming Pangandaran sudah terbukti menguntungkan bahkan di skala rumah tangga, 2. Kerapu dan lobster berpotensi menjadi komoditas unggulan ekspor, namun membutuhkan pengelolaan berkelanjutan agar tidak jatuh pada open access tragedy.
Proyeksi skala industri (KKP, 2021): Dengan mengadopsi model KJA Offshore Perinus–Norwegia (diameter 25,5 m, kedalaman 15 m, 8 unit jaring), potensi produksi per unit mencapai 816 ton/tahun.
"Jika 5 unit diterapkan di Pangandaran, maka produksi tahunan bisa mencapai ±4.000 ton dengan nilai ekonomi USD 20–30 juta/tahun (bergantung harga
ekspor)," katanya.
Pangandaran memiliki peluang besar untuk bertransformasi dari subsistence-scale aquaculture menuju industrial-scale offshore aquaculture, yang mampu memasok pasar Asia Timur dengan standar global
Dampak sosial-ekonomi offshore aquaculture Pangandaran
Prof. Rokhmin Dahuri mendorong offshore aquaculture sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian kelautan Indonesia, termasuk di Pangandaran, dengan potensi menciptakan lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat melalui budidaya komoditas bernilai tinggi seperti rumput laut dan biota lainnya, serta pemanfaatan potensi maritim secara inovatif untuk menjadi produsen di rantai pasok global.
* 30% penduduk Pangandaran bergantung pada perikanan tradisional (Bioflux, 2023), • Offshore → peluang 1.000 pekerja × Rp 4 juta/bulan = Rp 48 miliar/tahun ke ekonomi lokal.
* Dorong pembangunan pesisir: pelabuhan kecil, cold storage, transportasi, pendidikan vokasi, • Pasok stabil untuk UMKM kuliner (abon, seafood, keripik rumput laut).
* Desa wisata → ekowisata edukatif (kunjungan keramba + kuliner laut), • HDI berpotensi naik 3–5 poin dalam 10 tahun (World Bank, 2021).
Dampak Sosial Ekonomi dan Pariwisata
Membangun sinergi baru, antara lain, Lapangan Kerja Lokal: 5 unit KJA Offshore dapat menyerap 200–250 pekerja langsung, plus multiplier effect di logistik & pengolahan (GSJ, 2019).
Pemberdayaan Nelayan: Alih profesi dari penangkap → pembudidaya global melalui koperasi/community-based model (Bioflux, 2023).
Sinergi Wisata Bahari: Sea farming + eduwisata menjadikan keramba sebagai atraksi wisata sekaligus pusat riset (ERIA, 2023).
Risiko Sosial: Potensi konflik ruang laut, resistensi masyarakat, dan marginalisasi bila hanya dikuasai korporasi besar.
Rekomendasi Mitigasi: Pentahelix governance, partisipasi masyarakat sejak awal (co-design), serta CSR & benefit-sharing untuk desa dan konservasi laut.
Tantangan Budidaya KJA Offshore Pangandaran
* Gelombang tinggi & badai Samudera Hindia → perlu
teknologi keramba tahan ombak (submersible cages) (FAO, 2022).
* Kerentanan ekosistem: 30–50% terumbu karang alami bleaching, menurunkan populasi ikan (Ahmady & Rahman, 2025).
* Alih profesi nelayan tangkap → butuh pelatihan, modal, dan kelembagaan koperasi (DKPKP, 2023).
* Infrastruktur pendukung masih terbatas: cold chain, pasar ikan modern, processing plant (RPJMD, 2021–2026).
* Risiko degradasi habitat lobster & ikan karang → butuh hatchery & regulasi budidaya ketat (Bioflux, 2023).
Kemudian, hulu rantai pasok offshore Pangandaran: 1. Benih (Seed Supply) Kerapu & lobster masih bergantung benih alam → rawan overfishing & regulasi KKP. Kakap putih hatchery sudah ada (Lampung, Bali) tapi distribusi ke Pangandaran belum stabil.bMitigasi: bangun hatchery lokal dengan dukungan UNPAD & KKP.
2. Pakan (Feed Supply): Biaya pakan 60–70% dari total produksi (Henriksson et al., 2019).
Masih banyak pakai ikan rucah, tidak efisien & merusak stok laut. Solusi: pellet high protein + bahan substitusi (alga, serangga, SCP). Target FCR <1,5 untuk efisiensi & minim limbah.
3. Infrastruktur Hulu KJA offshore standar industri (Norwegia) butuh investasi Rp 35–40 miliar/unit.
Pangandaran masih kekurangan pelabuhan modern, cold storage, pabrik es, pusat logistik.Bottleneck distribusi akibat minim fasilitas cold chain.
Hilir Rantai Pasok: Distribusi, Pengolahan, Dan Akses Pasar
Panen dan Transportasi, • Panen cepat → kualitas menurun hanya dalam hitungan jam.l, • Cold chain wajib: truk pendingin dan kargo udara, • Akses terbatas: Bandara Nusawiru kecil, jalur darat ke Jakarta panjang,
2. Pengolahan (Processing), • Saat ini dominan jual segar → nilai tambah rendah, • Solusi: processing plant lokal (fillet, frozen, value added), • Produk turunan: nugget, kolagen, fish oil, chitosan, • World Bank (2021): pengolahan dapat menambah +30– 40% nilai ekspor.
3. Akses Pasar• Ekspor premium: lobster hidup ke HK, China, Taiwan. • Domestik premium: hotel & restoran (Jakarta, Bali), • Mass market: fillet barramundi untuk
ritel modern, • Industrial: rumput laut → kosmetik, farmasi, pangan.
4. UMKM & Desa Wisata, • UMKM lokal: abon, bakso ikan, olahan beku. • Desa wisata → seafood tourism hub (budidaya + kuliner).
Memastikan kualitas melalui panen cepat dan rantai dingin, Meningkatkan nilai melalui produk turunan dan fasilitas lokal, Memperluas jangkauan melalui ekspor premium dan pasar domestik, Mendukung usaha kecil dan pariwisata berbasis komunitas.
Kunci Keberhasilan Negara-bangsa Dalam Industri Akuakultur
* Strategi Nasional Jelas: Negara maju punya arah kebijakan yang konsisten dan mendukung keterlibatan sektor swasta, • Kolaborasi Pemerintah – Industri: Sinergi kuat jadi kunci inovasi, ketahanan produksi, dan perluasan pasar ekspor, • Ekspor Tinggi: Mencerminkan efisiensi, kualitas, serta kepatuhan pada standar global produk akuakultur
Benchmarking Global: Studi Kasus Norwegia & Vietnam
Norwegia – High-Tech Salmon Farming: • Perairan dingin, investasi USD 5–10 juta/keramba.
* Teknologi: submersible cages, AI feeding, sensor satelit, biosecurity ketat.
* Produksi >1,4 juta ton salmon/tahun (FAO, 2021).
* Pelajaran: butuh R&D berkelanjutan, adopsi IoT & AI, regulasi ketat.
Vietnam – Low-Cost Mariculture
* Perairan tropis & teluk dangkal, budidaya kerapu, kakap, lobster (floating cages sederhana).
* Pasar besar: ekspor ke China & Hong Kong.
* Masalah: pencemaran & penyakit (biosecurity lemah).
* Pelajaran: perlu IMTA, eco-label, dan sertifikasi global (ASC/MSC).
China & Kanada : Skala Besar & Model Imta
China – Skala Besar & Diversifikasi
* Produksi >5 juta ton/tahun, mencakup kerapu, tiram, rumput laut, teripang (FAO, 2022).
* Kekuatan: skala ekonomi & diversifikasi produk(pangan, farmasi, kosmetik).
* Tantangan: pencemaran, overcapacity, isu kualitas produk.
* Pelajaran: perlunya diversifikasi komoditas + standar kualitas & traceability. Kanada – Pioneer IMTA
* Memelopori IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture): salmon + rumput laut + kerang.
* Mampu mengurangi limbah organik hingga 30%, meningkatkan pendapatan petani (Henriksson et al., 2019).
* Keberhasilan ditopang riset universitas & regulasi pemerintah.
* Pelajaran: IMTA tropis (ikan + lobster + rumput laut) → peluang pilot project pertama di Indonesia.
Rokhmin Dahuri yang juga Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) itu menegaskan pentingnya harmonisasi tiga sektor strategis di wilayah pesisir: perikanan budidaya (mariculture), pariwisata bahari, dan perikanan tangkap. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa Pangandaran memiliki potensi besar untuk menjadi model nasional dalam integrasi pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan produktif.
Ia menekankan pentingnya kesesuaian lokasi kegiatan dengan RTRW (RZWP3K) Kabupaten Pangandaran yang telah diselaraskan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Harmonisasi ini menjadi fondasi agar budidaya laut, wisata bahari, dan aktivitas nelayan dapat berjalan berdampingan tanpa saling mengganggu.
“Ketiganya bisa berjalan beriringan asalkan ditata sesuai RTRW yang benar dan terintegrasi dengan RTRW provinsi dan nasional,” ujar Prof. Rokhmin.
Ia menyampaikan pandangan strategis terkait pengembangan offshore aquaculture di Pangandaran sebagai pilar ekonomi biru berstandar global. Menurutnya, wilayah ini memiliki peluang besar untuk naik kelas dari budidaya skala rumah tangga menuju industri ekspor bernilai puluhan juta dolar per tahun.
“Sea farming di Pangandaran sudah terbukti menguntungkan bahkan di level keluarga. Sekarang saatnya naik ke level industri,” ujarnya.
Rokhmin memaparkan, komoditas seperti kerapu dan lobster memiliki potensi besar sebagai unggulan ekspor, asalkan dikelola secara berkelanjutan agar tidak mengalami tragedi akses terbuka (open access tragedy).
Berdasarkan proyeksi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP, 2021), jika Pangandaran mengadopsi model KJA offshore seperti kolaborasi Perinus–Norwegia (8 jaring, kapasitas 816 ton/unit/tahun), maka cukup 5 unit untuk menghasilkan 4.000 ton produksi/tahun dengan nilai ekonomi USD 20–30 juta tergantung harga ekspor global.
Namun, ia juga menekankan sejumlah tantangan serius, antara lain:
- Gelombang tinggi dan badai Samudera Hindia, yang mengharuskan penggunaan submersible cages tahan ombak.
- Kerentanan ekosistem, seperti bleaching pada 30–50% terumbu karang yang menurunkan stok ikan.
- Alih profesi nelayan tangkap yang memerlukan pelatihan, kelembagaan koperasi, dan akses modal.
- Minimnya infrastruktur seperti cold chain, pasar ikan modern, dan pabrik pengolahan.
- Ancaman degradasi habitat lobster, yang butuh hatchery dan regulasi ketat.
“Dengan manajemen profesional, inovasi teknologi, dan dukungan infrastruktur, Pangandaran bisa menjadi pusat offshore aquaculture kelas dunia, memasok pasar Asia Timur dengan standar global,” tandasnya.
Transformasi pesisir Pangandaran menuju kawasan maritim berkelas dunia kian nyata. Prof. Rokhmin Dahuri memaparkan strategi harmonisasi tiga sektor utama: perikanan budidaya, pariwisata, dan perikanan tangkap, dalam sebuah forum strategis yang digelar pekan ini.
“Pangandaran punya potensi luar biasa untuk menjadi model pembangunan pesisir yang berkelanjutan dan berkelas global,” ujar Rokhmin.
Budidaya Laut Ramah Lingkungan dan Bernilai Wisata
Duta Kehormatan Kepulauan Jeju Dan Busan Metropolitan City, Korea Selatan itu menekankan bahwa budidaya laut seperti KJA (Karamba Jaring Apung) harus ramah lingkungan dan menerapkan Best Aquaculture Practices. Limbah budidaya tidak boleh melebihi kapasitas asimilasi lingkungan, dan operasionalnya tidak boleh mengganggu jalur wisata laut maupun aktivitas nelayan.
Komoditas unggulan yang disarankan untuk dibudidayakan meliputi lobster, barramundi, kerapu, dan rumput laut yang cocok dengan karakter oseanografis Pangandaran. Produk marikultur seperti lobster, cobia, dan bawal bintang juga menjadi daya tarik kuliner yang dicari wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Dengan desain KJA yang indah, kuat, dan bersih, budidaya laut bisa menjadi destinasi wisata tersendiri seperti di Norwegia, Singapura, dan Thailand. Wisatawan bisa ikut memberi pakan ikan, atau menikmati kuliner laut segar langsung dari lokasi,” paparnya.
Kegiatan marikultur dengan Karamba Jaring Apung (KJA) di Pangandaran diarahkan untuk menerapkan prinsip Best Aquaculture Practices dan zero-waste. Komoditas unggulan seperti kerapu, barramundi, lobster, dan rumput laut dipilih berdasarkan kesesuaian oseanografis lokal.
Menariknya, Prof. Rokhmin menyebut bahwa KJA yang dibangun dengan bahan HDPE yang kuat dan estetis bisa menjadi destinasi wisata tersendiri.
“Wisatawan bisa ikut memberi pakan, memancing, bahkan menikmati kuliner laut segar langsung dari sumbernya,” ujarnya.
Menuju Skala Industri
Dengan mengadopsi model KJA offshore Perinus Norwegia, Pangandaran berpotensi menghasilkan 4.000 ton ikan per tahun, bernilai ekonomi USD 20–30 juta.
“Ini bukan mimpi. Pangandaran bisa menjadi pemasok utama pasar Asia Timur,” tegas Prof. Rokhmin, yang juga Ketua Dewan Pakar Aspeksindo (Asosiasi Pemerintah Daerah Pesisir dan Kepulauan se Indonesia) itu.
Namun, ia juga mengingatkan tantangan serius: gelombang tinggi Samudera Hindia, bleaching terumbu karang, dan keterbatasan infrastruktur seperti cold chain dan pasar ikan modern. Alih profesi nelayan tangkap ke budidaya juga memerlukan pelatihan dan dukungan kelembagaan koperasi.
Lalu, Rokhmin Dahuri memaparkan tiga belas permasalahan dan tantangan dalam pembangunan perikanan budidaya di Indonesia, antara lain:
1. Sebagian besar usaha perikanan budidaya dilakukan secara tradisional (low technology), berskala Usaha Kecil dan Mikro (tidak memenuhi economy of scale), tidak menerapkan ISCMS, tidak mengaplikasikan Best Aquaculture Practices, dan tidak mengikuti prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
Sehingga, tingkat pemanfaatan, produktivitas, efisiensi, daya saing, dan sustainability usaha perikanan budidaya pada umumnya rendah, pembudidaya banyak yang miskin, dan kontribusi bagi perekonomian (PDB, nilai ekspor, pajak, PNBP, dan PAD) rendah.
2. Harga pakan berkualitas terus meningkat, karena semakin terbatasnya bahan baku utama (fishmeal) dari pakan ikan (udang).
3. Keterbatasan penggunaan bibit (broodstock), benih, dan benur unggul (SPF, SPR, dan fast growing) dan
bersitifikat (certified), karena keterbatasan supply (hatchery) atau para pembudidaya tergoda beli benih/benur uncertified, karena harga murah.
4. Keterbatasan sarana produksi lainnya, seperti kincir air (pedal wheel) tambak, growth stimulant, dan obat-obatan.
5. Wabah penyakit yang menyebabkan rendahnya produktivitas, bahkan kegagalan panen.
6. Infrastruktur perikanan budidaya (seperti irigasi tambak, dan kolam ikan); infrastruktur dasar (seperti jaringan jalan, listrik, telkom, internet, air bersih, dan pelabuhan); dan Sistem Logistik masih belum memadai.
7. Pencemaran ekosistem perairan dari sektor pembangunan lainnya, semakin berkurangnya biodiversity, dan kerusakan lingkungan lainnya.
8. Dampak Perubahan Iklim Global, banjir, dan bencana alam lainnya.
9. Lemahnya dukungan R & D untuk inovasi teknologi on-farm maupun offfarm Perikanan Budidaya.
10. Kualitas SDM (kowledge, skills, expertise, dan work ethics) pembudidaya relatif masih rendah.
11. Lemahnya spirit “Indonesia Aquaculture Incroporated”
12. Iklim investasi (seperti perizinan, RTRW, konsisten kebijakan pemerintah, keamanan berusaha, keadilan dan kepastian hukum) kurang atau tidak kondusif.
Contoh: kriminalisasi petambak di Karimun Jawa, kontroversi Budidaya KJA di Laut Pangandaran, intimidasi terhadap pembudidaya Ikan Nila di Danau Toba, dan pungli serta teror oleh oknum aparat maupun preman terhadap petambak udang di berbagai daerah (Lampung, Bengkulu, Deli Serdang, Medan, dll).
13. Kebijakan politik ekonomi (monter, fiskal, kredit perbankan, RTRW, ekspor – impor, dan ketenagakerjaan) belum kondusif bagi kinerja dan tumbuhkembangnya Perikanan Budidaya.
Prof. Rokhmin Dahuri menguraikan strategi harmonisasi pembangunan perikanan budidaya, pariwisata, dan perikanan tangkap di perairan laut untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Pangandaran.
1. Lokasi ketiga sektor pembangunan itu harus sesuai dengan RTRW (RZWP3K) Kab. Pangandaran yang asli (benar), yang sudah dipaduserasikan dengan RTRW Propinsi Jabar dan RTRW Nasional.
2. Kegiatan Perikanan Budidaya (Mariculture) dengan menggunakan KJA (Karamba Jaring Apung) harus menerapkan Best Aquaculture Practices dan ramah lingkungan, tidak membuang limbah yang melebihi kapasitas asimilasi wilayah perairan pesisir Pangandaran (usahakan bisa zero-waste), dan tidak mengganggu lalu-lintas aktivitas pariwisata maupun penangkapan ikan oleh nelayan.
3. Komoditas (spesies) yang dibudidayakan: kerapu, barramundi, lobster, rumput laut, dan lainnya yang cocok (suitable) dengan kondisi oseanografis dan klimatologis setempat.
Keunggulan Budidaya KJA Offshore Pangandaran
* SDM kuat: ada 1.852 nelayan (1.672 laut, 180 PUD) dan 3.269 pembudidaya aktif (KKP, 2023).
* Kondisi oseanografi sesuai: suhu 27–30°C, salinitas 33–34 ppt, DO 5,5–6,5 mg/L, arus <100 cm/s, kedalaman 10–30 m (Bioflux, 2023; GSJ, 2019).
* Komoditas unggulan bernilai tinggi: kakap putih, kerapu, lobster duri, Ikan Cobia, rumput laut (FAO, 2022; KKP, 2023).
* Basis sosial-ekonomi: Pangandaran punya tradisi nelayan tangkap & wisata bahari, mudah dikembangkan jadi sea farming + edu-tourism.
Pada 2023, perikanan Pangandaran menghasilkan 2.891,89 ton tangkap laut dengan unggulan udang, kembung, dan layur, serta 324 ton budidaya dengan
unggulan udang vaname, nila, dan lele.
* Kabupaten Pangandaran di pesisir selatan Jawa Barat memiliki garis pantai ±91 km yang langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Dengan luas wilayah 168.509 ha, terdiri dari 67.340 ha perairan laut. (BPS, 2021)
* Perairan Pangandaran ideal untuk budidaya laut dengan suhu 27–30°C, salinitas 33–34 ppt, DO 5,5–6,5 mg/L, arus kurang 100 cm/s, dan kedalaman 10–30 m
(Bioflux, 2023; GSJ, 2019).
* Ekosistem pesisirnya terdiri dari terumbu karang, mangrove, dan padang lamun, namun 30–50% karang mengalami pemutihan akibat iklim (Ahmady & Rahman, 2025).
4. Dengan bahan KJA yang bagus, indah, kuat, dan ramah lingkungan, seperti HDPE (High Density Poly Etheline), maka seperti halnya di negara-negara lain (Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Hongkong, China, Norwegia, AS, Canada, dan Chile); budidaya ikan maupun lobster dengan KJA di laut dapat dijadikan obyek/destinasi wisata, seperti mancing, memberi pakan, dll.
Selain itu, produk dari mariculture (seperti lobster, barramundi, kerapu, bawal Bintang, cobia, dan rajungan) merupakan kuliner favorite (yang dicari) bagi sebagian besar wisatawan, baik domestik maupun wisman (wisatawan manca negara).
5. Hasil tangkapan para nelayan, seperti ikan kecil (rucah) dan kekerangan merupakan pakan yang bagus dan utama bagi lobster budidaya.
6. Berbagai aktivitas pariwisata dan penangkapan ikan pun tidak boleh mencemari lingkungan perairan laut Pangandaran.
7. Perkuat dan kembangkan kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Swasta/Industri, Akademisi/Peneliti, Masyarakat, dan Media Masa): R & D, Capacity Building, Investasi dan Bisnis, Monev, dan penciptaan Iklim Investasi Kondusif.
Ia juga menyoroti pentingnya investasi pada infrastruktur seperti cold chain, pasar ikan modern, hatchery, dan pelatihan SDM agar Pangandaran bisa menjadi sentra akuakultur berstandar global.
“Pangandaran bisa menjadi laboratorium hidup pembangunan pesisir Indonesia. Tapi harus kita bangun bersama, dengan ilmu, teknologi, dan semangat gotong royong,” tutup Anggota Dewan Penasihat Ilmiah Internasional Pusat Pengembangan Pesisir dan Kelautan, Universitas Bremen, Jerman itu.